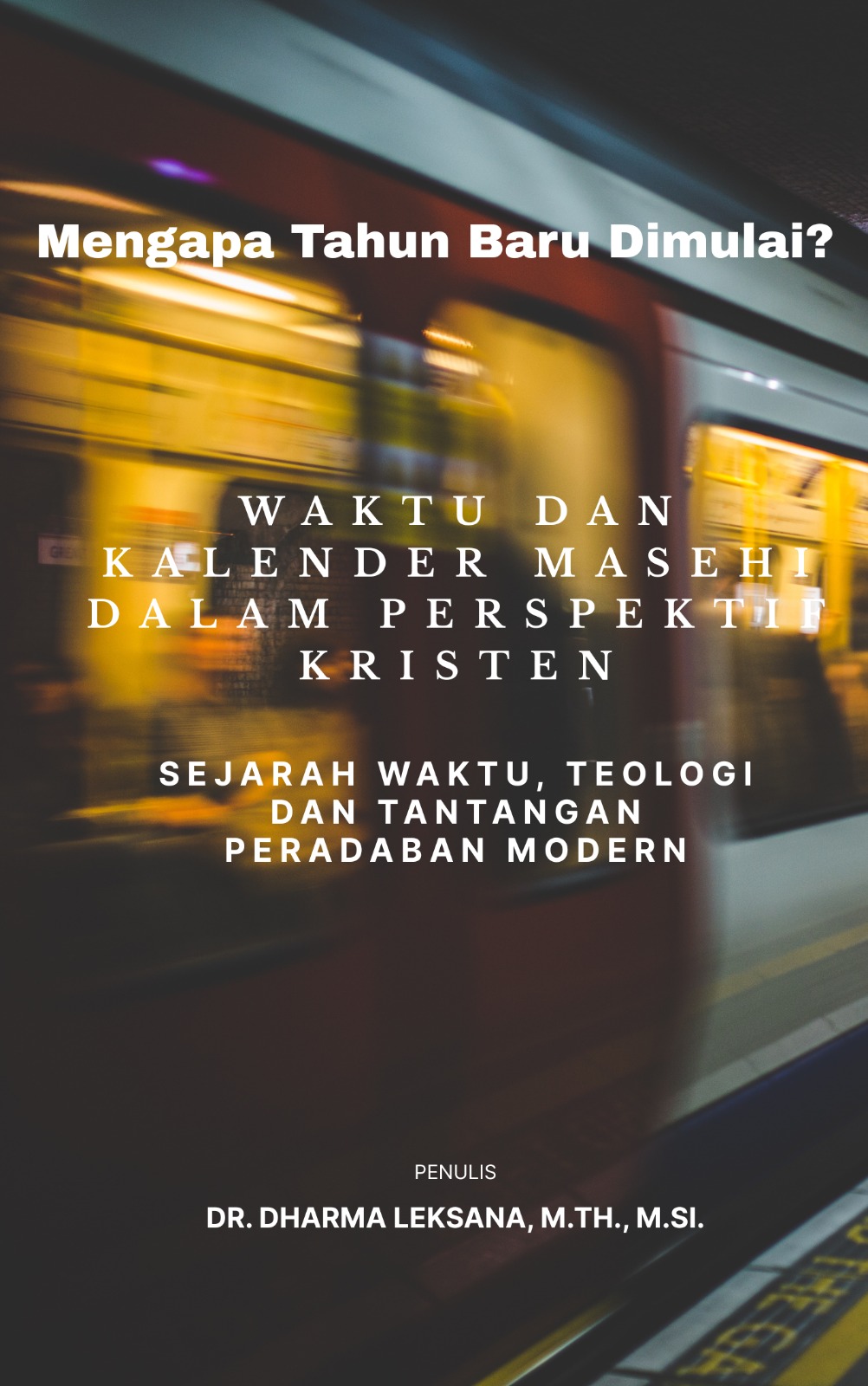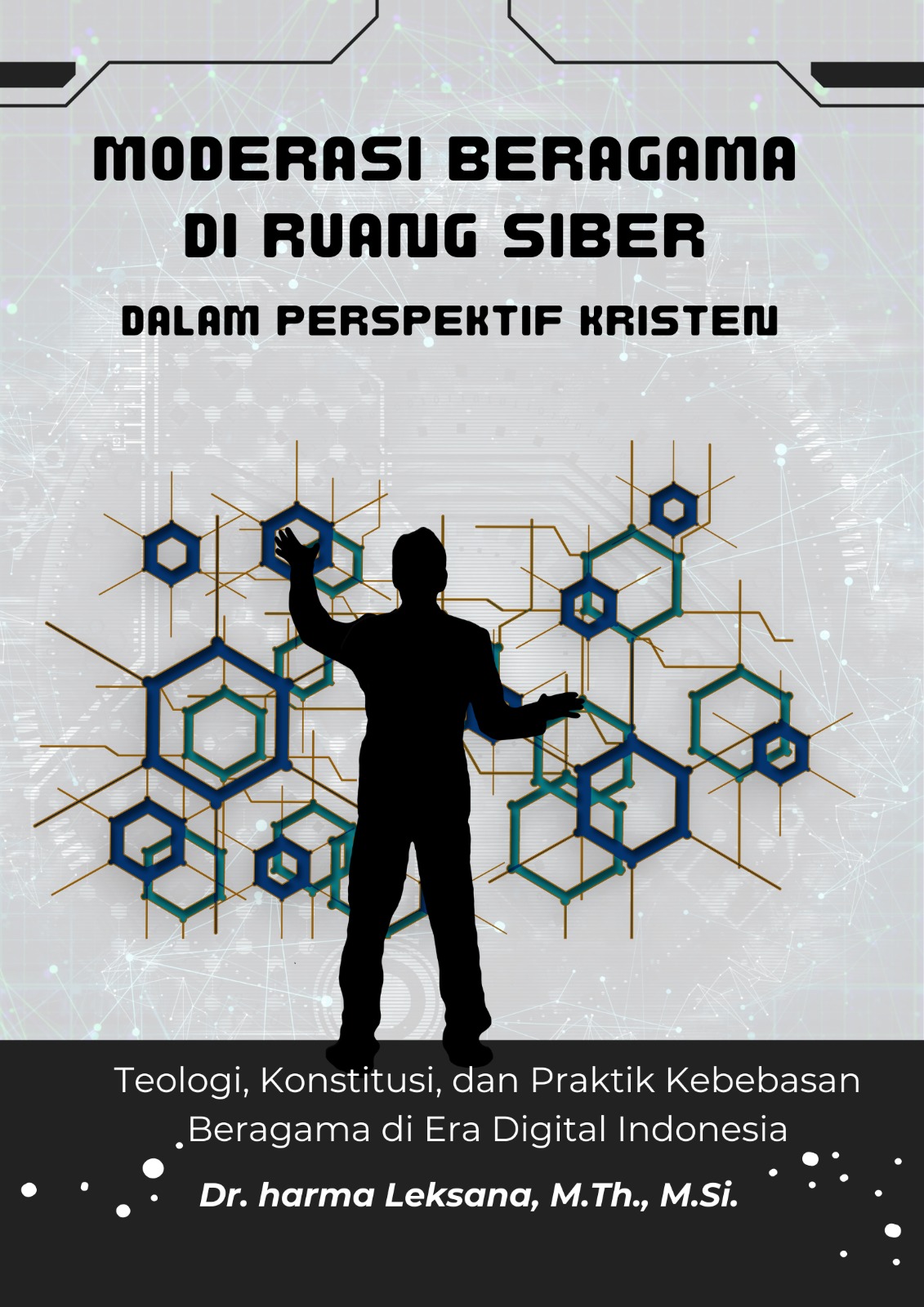Membongkar Makna di Era Digital: Relevansi Filsafat Bahasa Wittgenstein, Saussure, Austin, dan Chomsky

Oleh : Dharma Leksana, S.Th., M.Si.
Teologi.digital – Jakarta, Era digital telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Banjir informasi, interaksi instan melalui teks, gambar, dan video, serta kemunculan kecerdasan buatan yang mampu berbahasa, semuanya menghadirkan lanskap linguistik yang baru dan kompleks. Di tengah derasnya arus komunikasi digital ini, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bahasa—bagaimana makna diciptakan, bagaimana konteks memengaruhinya, bagaimana bahasa digunakan untuk bertindak, dan apa struktur dasarnya—menjadi semakin krusial. Filsafat bahasa, dengan wawasan dari para pemikir kuncinya seperti Ludwig Wittgenstein, Ferdinand de Saussure, J.L. Austin, dan Noam Chomsky, menawarkan perangkat analisis yang tak ternilai untuk memahami dinamika bahasa di peradaban digital.
1. Wittgenstein: Makna sebagai Penggunaan dalam “Permainan Bahasa” Digital
Ludwig Wittgenstein, terutama dalam fase pemikiran “akhir”-nya, menekankan bahwa makna sebuah kata atau kalimat tidak terletak pada hubungan abstrak dengan objek, melainkan pada penggunaannya dalam konteks sosial tertentu, yang ia sebut sebagai “permainan bahasa” (language games). Setiap komunitas atau aktivitas memiliki aturan main bahasanya sendiri.
- Relevansi di Era Digital: Konsep ini sangat relevan untuk memahami bagaimana bahasa berfungsi di berbagai platform digital.
- Komunitas Online: Forum internet, grup media sosial (Facebook, WhatsApp), komunitas gamer, atau bahkan kolom komentar memiliki “permainan bahasa” mereka sendiri, lengkap dengan jargon, singkatan, meme, dan etiket komunikasi (atau ketiadaannya) yang khas. Makna sebuah postingan atau komentar seringkali hanya bisa dipahami sepenuhnya oleh mereka yang “bermain” dalam konteks tersebut.
- Emoji dan Meme: Ini adalah bentuk “penggunaan” bahasa visual yang maknanya sangat bergantung pada konteks budaya digital saat itu. Sebuah emoji atau meme bisa memiliki arti berbeda tergantung pada platform dan komunitas penggunanya.
- Misunderstanding Lintas Konteks: Tanpa konteks sosial yang kaya seperti dalam interaksi tatap muka (intonasi, ekspresi wajah), kesalahpahaman dalam komunikasi digital sering terjadi karena asumsi “permainan bahasa” yang berbeda antara pengirim dan penerima.
2. Saussure: Bahasa Digital sebagai Sistem Tanda yang Berkembang
Ferdinand de Saussure, bapak linguistik struktural, melihat bahasa sebagai sistem tanda (signs) yang terdiri dari penanda (signifier – bunyi/tulisan) dan petanda (signified – konsep). Hubungan antara keduanya bersifat arbitrer (tidak ada hubungan alamiah), dan makna muncul dari relasi dan perbedaan antar tanda dalam sistem tersebut.
- Relevansi di Era Digital:
- Evolusi Tanda Digital: Era digital melahirkan banyak penanda baru: ikon, emoji, GIF, hashtag (#). Tanda-tanda ini memperoleh maknanya melalui konvensi dan penggunaannya dalam sistem komunikasi digital. Hashtag, misalnya, berfungsi sebagai penanda topik atau komunitas dalam sistem media sosial.
- Keterbatasan dan Struktur Medium: Platform digital seringkali membatasi cara kita berbahasa (misalnya, batas karakter Twitter). Ini memaksa pengguna untuk berkreasi dalam sistem tanda yang terbatas, melahirkan singkatan atau gaya bahasa baru, menunjukkan bagaimana struktur medium memengaruhi sistem bahasa.
- Arbitraritas dan Perubahan Makna: Sifat arbitrer tanda memungkinkan makna kata atau simbol digital berubah dengan cepat. Slang internet atau makna meme bisa bergeser dalam waktu singkat tergantung pada tren dan penggunaannya dalam sistem online.
3. J.L. Austin: Tindak Tutur dalam Interaksi Digital
J.L. Austin menggeser fokus dari bahasa sebagai deskripsi realitas semata menjadi bahasa sebagai tindakan (speech acts). Saat berbahasa, kita tidak hanya mengatakan sesuatu (locutionary act), tetapi juga melakukan sesuatu (illocutionary act – misal: bertanya, memerintah, berjanji) dan seringkali menghasilkan efek tertentu pada pendengar (perlocutionary act).
- Relevansi di Era Digital:
- Tindakan Melalui Klik dan Teks: Setiap interaksi digital bisa dianalisis sebagai tindak tutur. Mengeklik “Like” atau “Share” adalah tindakan menyetujui atau menyebarkan. Menulis komentar bisa berupa tindakan bertanya, mengkritik, memuji, atau bahkan mengancam (hate speech). Melakukan transaksi online adalah serangkaian tindak tutur kontraktual.
- Ambiguitas Niat (Illocutionary Force): Di dunia digital, ketiadaan isyarat non-verbal sering membuat niat di balik tuturan (illocutionary force) menjadi ambigu. Sarkasme sulit terdeteksi, permintaan bisa terdengar seperti perintah, dan permintaan maaf online mungkin dirasa kurang tulus. Ini menyoroti pentingnya kejelasan dan potensi kesalahpahaman dalam tindak tutur digital.
- Performativitas Identitas Online: Cara kita menggunakan bahasa di profil media sosial adalah tindakan membangun dan menampilkan identitas (performance of self).
4. Noam Chomsky: Struktur Bawaan dan Bahasa Artifisial
Noam Chomsky berpendapat bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa bawaan (innate), yang didasari oleh struktur tata bahasa universal (Universal Grammar). Kemampuan ini memungkinkan manusia tidak hanya meniru, tetapi juga menghasilkan kalimat-kalimat baru yang tak terbatas (generative grammar).
- Relevansi di Era Digital:
- Adaptasi Kemampuan Bawaan: Kemampuan generatif bawaan inilah yang memungkinkan manusia beradaptasi dengan cepat dan kreatif menggunakan berbagai medium komunikasi digital baru, menciptakan ekspresi dan struktur kalimat yang sesuai dengan platform tersebut.
- Natural Language Processing (NLP) & AI: Teori Chomsky tentang struktur dasar bahasa sangat berpengaruh dalam pengembangan AI yang berfokus pada pemrosesan dan generasi bahasa alami (seperti model GPT). AI mencoba meniru kemampuan generatif manusia dengan menganalisis pola dan struktur dalam data bahasa yang sangat besar.
- Pertanyaan tentang Pemahaman AI: Filsafat Chomsky juga memicu pertanyaan penting: Apakah AI yang mampu menghasilkan teks mirip manusia benar-benar “memahami” bahasa seperti manusia dengan kemampuan bawaannya, atau hanya melakukan manipulasi simbol berdasarkan pola statistik? Ini menjadi perdebatan filosofis krusial di era AI generatif.
Sintesis: Mengapa Filsafat Bahasa Penting di Era Digital?
Pemikiran keempat filsuf ini, meskipun berbeda fokus, secara kolektif memberikan wawasan penting:
- Konteks adalah Kunci (Wittgenstein): Kita perlu sadar akan beragamnya “permainan bahasa” online untuk menghindari kesalahpahaman dan berkomunikasi secara efektif.
- Sistem Terus Berkembang (Saussure): Bahasa digital adalah sistem tanda yang dinamis; memahami strukturnya membantu kita menavigasi makna yang terus berubah.
- Kata adalah Tindakan (Austin): Setiap klik, ketikan, dan unggahan di dunia digital adalah sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi. Kesadaran ini penting untuk etika berkomunikasi online.
- Struktur Mendasari Kreativitas (Chomsky): Memahami struktur dasar bahasa membantu kita mengapresiasi adaptasi manusia dalam komunikasi digital dan memahami potensi serta keterbatasan AI berbahasa.
Secara umum, filsafat bahasa membekali kita dengan alat untuk:
- Menganalisis Makna: Membedah bagaimana makna diciptakan, dinegosiasikan, dan seringkali dimanipulasi dalam ruang digital.
- Memahami Komunikasi (dan Mis-): Mengidentifikasi sumber kesalahpahaman yang unik dalam interaksi online.
- Menilai Dampak Teknologi: Mengevaluasi secara kritis bagaimana platform dan algoritma membentuk cara kita berbahasa dan berpikir.
- Mengembangkan Literasi Digital Kritis: Bergerak melampaui kemampuan teknis menggunakan alat digital menuju pemahaman mendalam tentang implikasi linguistik dan sosialnya.
Last but not least, Jauh dari usang, filsafat bahasa justru menemukan relevansi baru yang mendesak di era digital. Wawasan dari Wittgenstein, Saussure, Austin, dan Chomsky membantu kita membongkar kompleksitas komunikasi online, memahami bagaimana makna dibentuk dan dinegosiasikan dalam konteks digital, serta menyadari bahwa setiap tuturan digital adalah tindakan yang membentuk realitas sosial kita. Di tengah dunia yang semakin termediasi oleh teknologi, kemampuan untuk menganalisis bahasa secara filosofis adalah kunci untuk navigasi yang sadar, komunikasi yang bertanggung jawab, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi manusia kontemporer.
Daftar Referensi dan Pustaka
I. Martin Heidegger
- Karya Primer Utama:
- Heidegger, Martin. Sein und Zeit (1927). (Diterjemahkan sebagai Being and Time atau Ada dan Waktu). Ini adalah karya fundamentalnya yang membahas Dasein, Ada-di-Dunia, temporalitas, otentisitas, dan fenomenologi hermeneutik. Fondasi utama untuk memahami analisis eksistensialnya.
- Heidegger, Martin. “Die Frage nach der Technik” (1954). (Diterjemahkan sebagai “The Question Concerning Technology” atau “Pertanyaan Perihal Teknik”). Esai krusial yang membahas hakikat teknologi modern dan konsep Gestell (Enframing). Sangat relevan untuk era digital. Sering ditemukan dalam kumpulan esai seperti The Question Concerning Technology and Other Essays.
- Heidegger, Martin. Unterwegs zur Sprache (1959). (Diterjemahkan sebagai On the Way to Language). Kumpulan esai yang mendalami hubungan antara pemikiran, bahasa, dan Ada, penting untuk aspek hermeneutiknya.
- Karya Pengantar dan Sekunder (Rekomendasi):
- Polt, Richard. Heidegger: An Introduction. Cornell University Press, 1999. Pengantar yang relatif mudah diakses ke pemikiran Heidegger.
- Dreyfus, Hubert L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I. MIT Press, 1991. Komentar mendalam (meskipun juga menantang) yang sangat berpengaruh terhadap Being and Time.
- Mulhall, Stephen. Heidegger and Being and Time. Routledge, 2nd ed., 2005. Pengantar yang baik dan terstruktur untuk karya utama Heidegger.
- Harman, Graham. Heidegger Explained: From Phenomenon to Thing. Open Court, 2007. Penjelasan yang mencoba menyederhanakan beberapa ide kunci.
II. Ludwig Wittgenstein
- Karya Primer Utama:
- Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus (1921). Karya awal yang berpengaruh, fokus pada hubungan logis antara bahasa, pikiran, dan dunia (teori gambar). Berbeda signifikan dari pemikiran lanjutnya.
- Wittgenstein, Ludwig. Philosophische Untersuchungen (1953). (Diterjemahkan sebagai Philosophical Investigations atau Penyelidikan-penyelidikan Filsafati). Karya utama dari fase pemikiran lanjutnya, membahas “permainan bahasa” (language games), makna sebagai penggunaan, dan kritik terhadap pandangan filsafat tradisional. Sangat relevan untuk diskusi kita.
- Karya Pengantar dan Sekunder (Rekomendasi):
- Kenny, Anthony. Wittgenstein. Harvard University Press, Revised ed., 2006. Pengantar klasik yang mencakup kedua periode pemikiran Wittgenstein.
- Monk, Ray. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius. Penguin Books, 1991. Biografi intelektual yang sangat dihormati, memberikan konteks pemikirannya.
- Glock, Hans-Johann. A Wittgenstein Dictionary. Blackwell Publishing, 1996. Kamus konsep-konsep kunci dalam pemikiran Wittgenstein.
- McGinn, Marie. Routledge Philosophy Guidebook to Wittgenstein and the Philosophical Investigations. Routledge, 2nd ed., 2013. Panduan yang fokus pada karya Philosophical Investigations.
III. Ferdinand de Saussure
- Karya Primer Utama:
- Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale (1916). (Diterjemahkan sebagai Course in General Linguistics). Buku fundamental yang disusun dari catatan kuliahnya oleh murid-muridnya. Meletakkan dasar linguistik struktural, membahas konsep tanda, signifier/signified, langue/parole, arbitraritas, dan nilai diferensial.
- Karya Pengantar dan Sekunder (Rekomendasi):
- Culler, Jonathan. Ferdinand de Saussure. Cornell University Press, Revised ed., 1986. Pengantar yang bagus dan ringkas tentang ide-ide utama Saussure dan dampaknya.
- Harris, Roy. Reading Saussure: A Critical Commentary on the Cours de linguistique générale. Duckworth, 1987. Analisis kritis terhadap teks utama Saussure.
- Buku-buku teks pengantar linguistik umumnya memiliki bab yang baik tentang Saussure dan strukturalisme.
IV. J.L. Austin
- Karya Primer Utama:
- Austin, J.L. How to Do Things with Words (1962). Kumpulan kuliah anumerta yang memaparkan teori tindak tutur (speech acts), membahas aspek lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Sangat penting untuk topik yang dibahas.
- Austin, J.L. Philosophical Papers. Oxford University Press, 3rd ed., 1979. Kumpulan makalahnya yang mencakup berbagai topik dalam filsafat bahasa dan epistemologi.
- Austin, J.L. Sense and Sensibilia. Oxford University Press, 1962. Kritik terhadap teori data inderawi (sense-data).
- Karya Pengantar dan Sekunder (Rekomendasi):
- Warnock, G.J. J. L. Austin. Routledge, 1989. Pengantar umum ke pemikiran Austin.
- Graham, Keith. J.L. Austin: A Critique of Ordinary Language Philosophy. Harvester Press, 1977. Analisis kritis terhadap metode filsafat Austin.
- Searle, John R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press, 1969. Pengembangan penting dari teori tindak tutur Austin oleh muridnya. (Meskipun karya Searle sendiri, ini relevan).
V. Noam Chomsky
- Karya Primer Utama (Fokus Linguistik):
- Chomsky, Noam. Syntactic Structures (1957). Karya awal yang merevolusi linguistik dengan memperkenalkan tata bahasa generatif.
- Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax (1965). Pengembangan lebih lanjut dari teori tata bahasa generatif (model Standar).
- Chomsky, Noam. Language and Mind (1968, diperluas 2006). Membahas hubungan antara studi bahasa dan studi pikiran, argumen tentang kemampuan bahasa bawaan.
- Karya Pengantar dan Sekunder (Rekomendasi):
- Lyons, John. Noam Chomsky. Penguin Books, Revised ed., 1977. Pengantar klasik (meskipun agak tua) ke ide-ide linguistik Chomsky.
- Smith, Neil. Chomsky: Ideas and Ideals. Cambridge University Press, 3rd ed., 2016. Pengantar komprehensif yang mencakup aspek linguistik dan politik pemikiran Chomsky.
- Buku-buku teks pengantar linguistik modern, sintaksis, atau psikolinguistik akan banyak membahas teori Chomsky.
VI. Referensi Umum Filsafat Bahasa & Aplikasi ke Era Digital
- Pengantar Filsafat Bahasa:
- Lycan, William G. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. Routledge, 3rd ed., 2018. Buku teks standar yang mencakup banyak tokoh dan topik utama.
- Martinich, A.P., and David Sosa (eds.). The Philosophy of Language. Oxford University Press, 6th ed., 2012. Antologi teks-teks klasik dan kontemporer.
- Aplikasi ke Era Digital (Contoh Arah Pencarian):
- Cari buku atau artikel di bidang: Philosophy of Technology, Digital Ethics, Cyberphilosophy, Communication Studies, Digital Rhetoric, Philosophy of Information.
- Beberapa nama yang mungkin relevan dalam diskusi ini: Luciano Floridi (Philosophy of Information), Charles Ess (Digital Ethics), Hubert Dreyfus (Kritik AI dari perspektif Heideggerian/Fenomenologi), Sherry Turkle (Psikologi Kehidupan Online).
- Contoh: Ess, Charles. Digital Media Ethics. Polity Press, 3rd ed., 2020. (Meskipun fokus etika, sering menyentuh isu bahasa dan komunikasi).
Note : Perlu diingat bahwa karya-karya primer filsafat, terutama Heidegger dan Wittgenstein, seringkali padat dan menantang. Membaca buku pengantar atau komentator terlebih dahulu bisa sangat membantu.