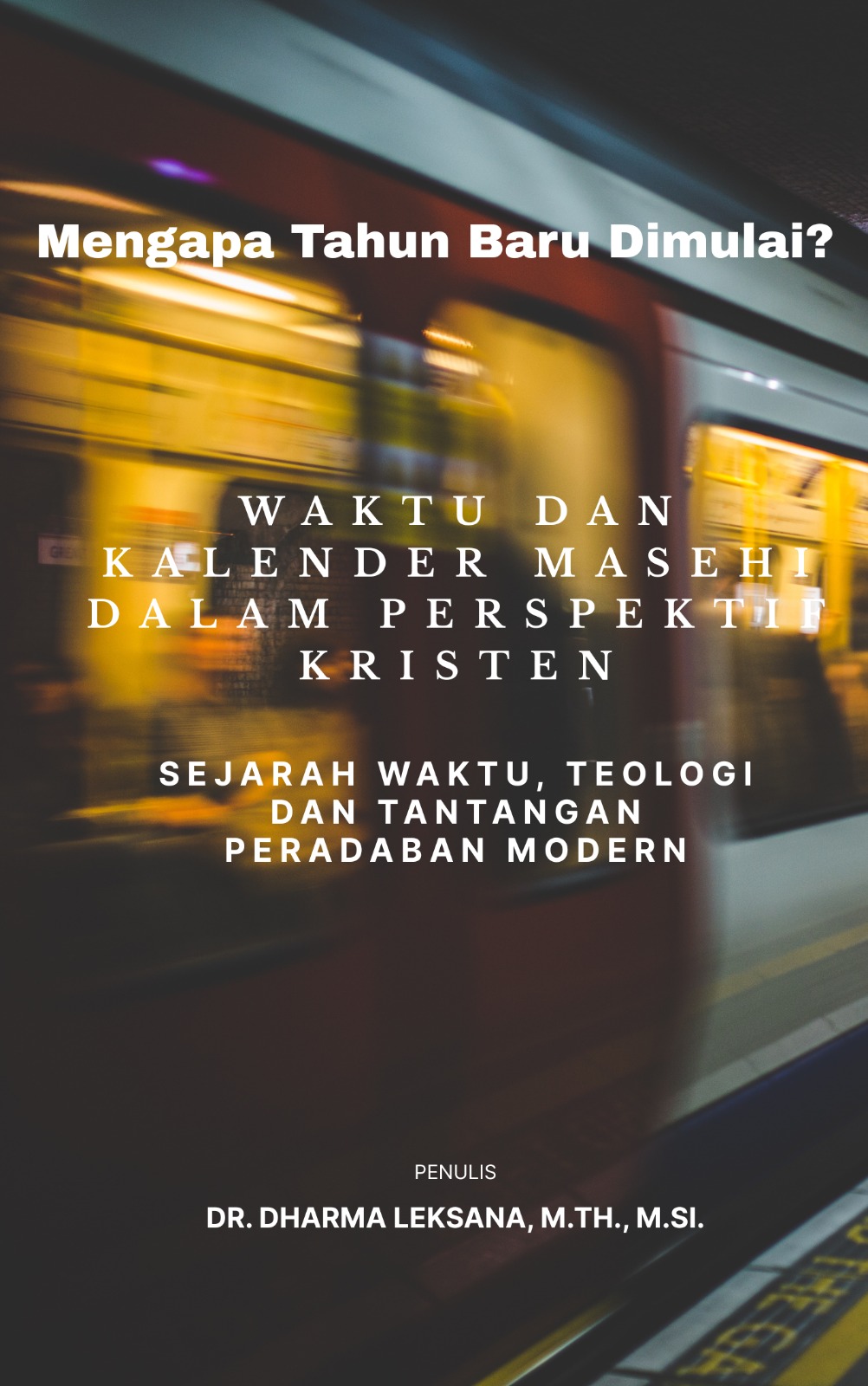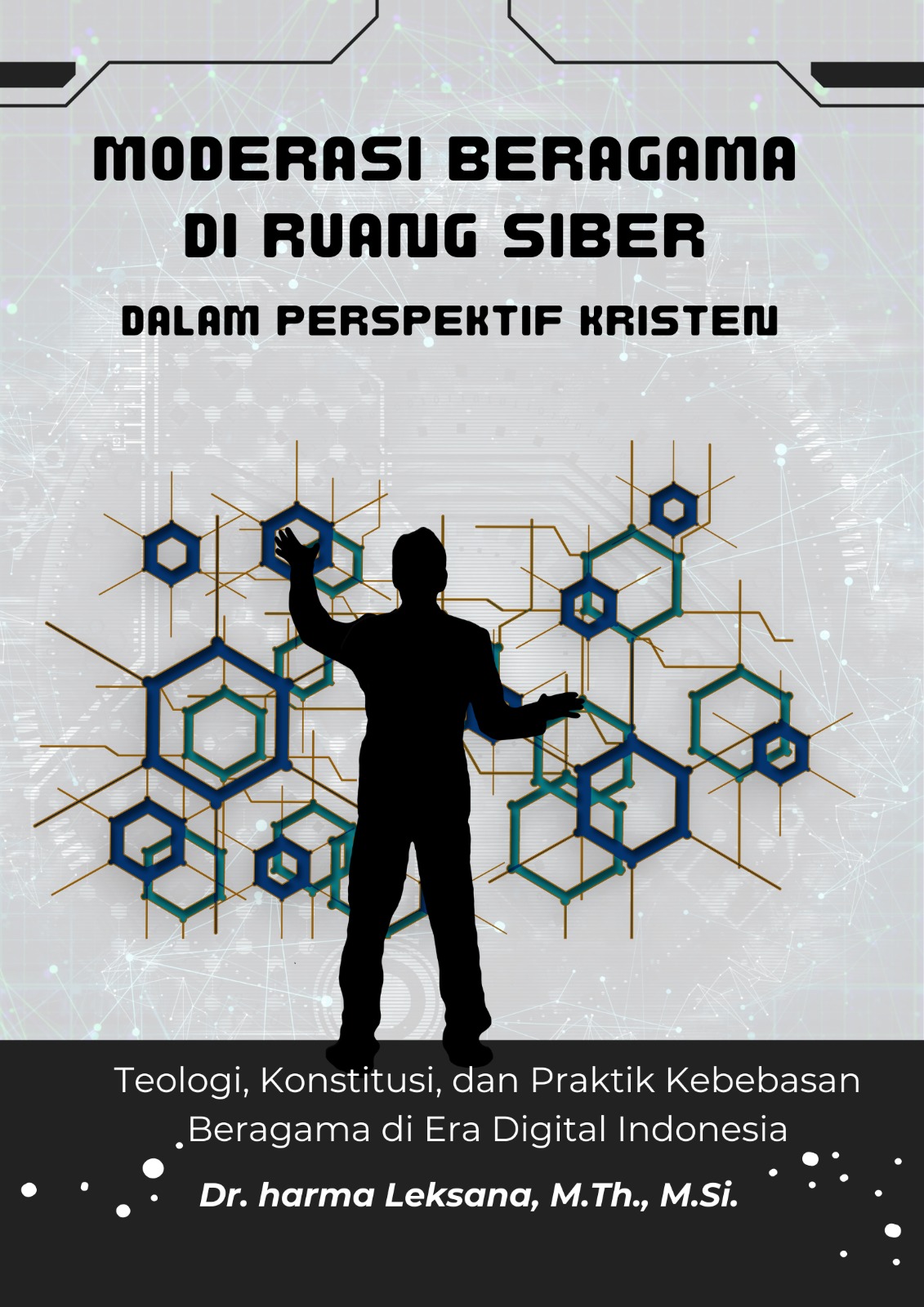Menjadi Gereja dalam Masyarakat di Era Digital: Sebuah Studi Eklesiologi Misioner dan Etika Sosial
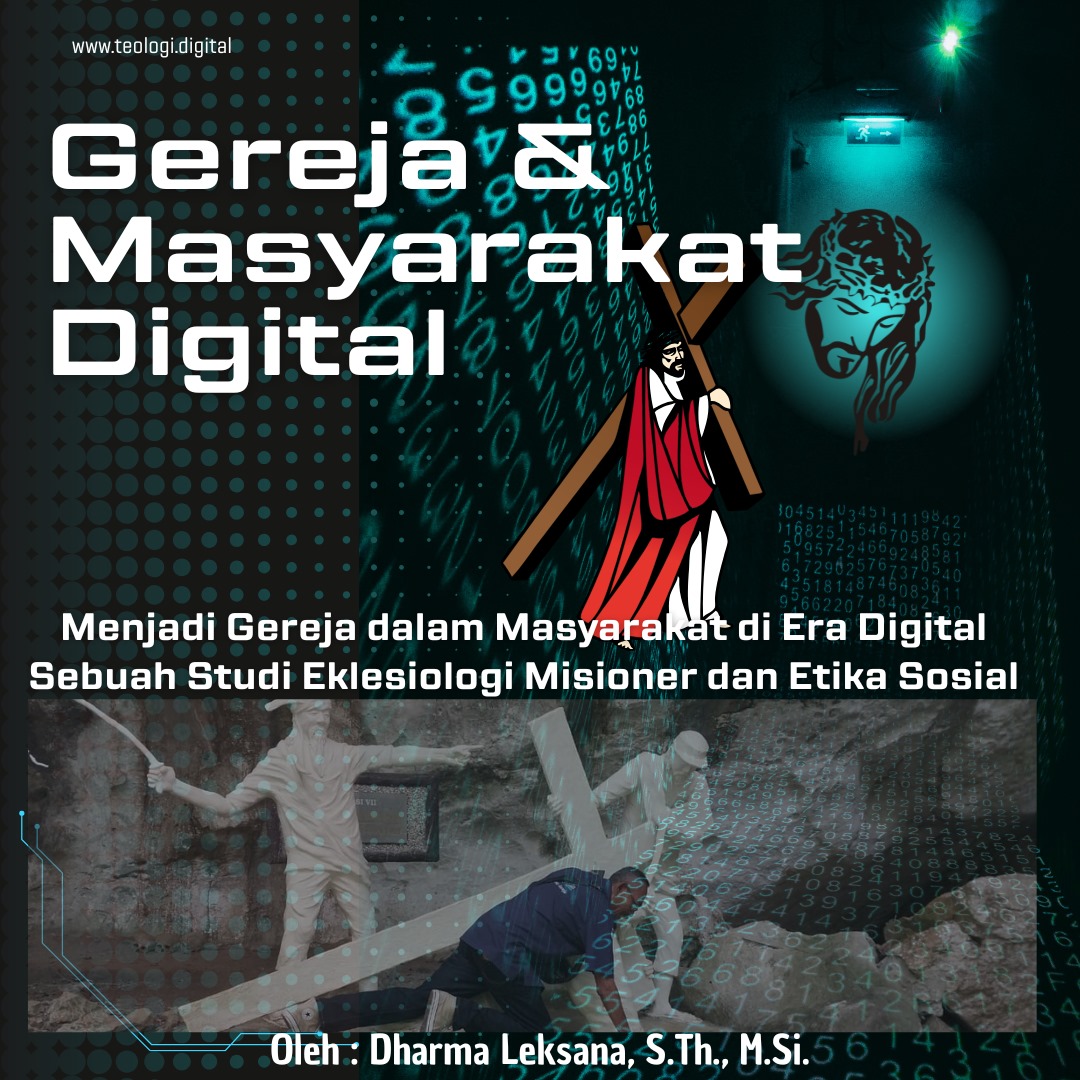
Oleh : Dharma Leksana, S.Th., M.Si.
Daftar Isi
Abstrak
- Pendahuluan
- Latar Belakang: Transformasi Sosial dan Tantangan Gereja di Era Digital
- Pentingnya Keterlibatan Gereja dalam Masyarakat Kontemporer
- Tujuan dan Struktur Laporan
- Memahami Gereja dan Masyarakat
- Hakikat Gereja: Perspektif Etimologis, Teologis, Sosiologis, dan Institusional
- Definisi Masyarakat: Konsep Sosiologis dan Unsur-unsurnya
- Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM): Fondasi Keterlibatan Holistik
- Peran dan Tujuan Gereja dalam Masyarakat
- Mandat Alkitabiah: Gereja sebagai Garam dan Terang Dunia (Matius 5:13-16)
- Tiga Tugas Panggilan Gereja: Koinonia, Marturia, dan Diakonia
- Tujuan Gereja Bermasyarakat: Mewujudkan Nilai-nilai Injil dan Kesejahteraan Bersama
- Landasan Teologis Keterlibatan Gereja dalam Masyarakat
- Perspektif Teolog dan Filsuf Kristen tentang Keadilan Sosial dan Pelayanan
- Inkarnasi Kristus sebagai Model Keterlibatan dan Solidaritas Gereja
- Imago Dei dan Missio Dei: Landasan Misi Sosial Gereja
- Masyarakat Digital: Karakteristik dan Dampaknya
- Definisi dan Ontologi Masyarakat Digital (Cyberspace)
- Dampak pada Interaksi Sosial, Komunikasi, dan Identitas
- Tantangan Etika dan Moralitas di Ruang Digital
- Menjadi Gereja dalam Masyarakat Digital: Tantangan dan Peluang
- Tantangan Pelayanan Gereja di Era Digital
- Peluang dan Strategi Adaptasi Gereja di Ruang Digital
- Landasan Teologis untuk Gereja Digital: Relevansi Soteriologi, Kristologi, dan Eskatologi
- Implementasi Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM) di Era Digital
- Keterlibatan Sosial dan Kesejahteraan Bersama melalui Platform Digital
- Pelayanan dan Kesaksian Digital: Membangun Komunitas dan Memberdayakan Umat
- Kerja Sama Lintas Sektor dan Advokasi Kebijakan Digital
- Pendidikan dan Pemberdayaan Digital: Contoh-contoh Praktis E. Peran Ganda Gereja: Menjaga Identitas dan Beradaptasi
- Kesimpulan dan Rekomendasi
- Ringkasan Temuan Kunci
- Rekomendasi Strategis untuk Gereja di Era Digital
- Arah Penelitian Lanjutan
Abstrak
Artikel ini menganalisis secara mendalam peran dan adaptasi Gereja dalam konteks masyarakat digital, dengan landasan teologis yang kuat dan integrasi konsep Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM).
Melalui studi literatur, tulisan ini mendefinisikan hakikat Gereja dan Masyarakat, mengidentifikasi peran dan tujuan Gereja bagi masyarakat, serta menggali landasan teologis dari pemikir Kristen. Analisis masyarakat digital mencakup karakteristik, dampak pada interaksi sosial, dan tantangan etika.
Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana Gereja dapat menjadi “garam dan terang” di era digital, menghadapi tantangan seperti disinformasi dan krisis identitas, sekaligus memanfaatkan peluang teknologi untuk pelayanan holistik yang transformatif, sejalan dengan prinsip-prinsip GGM.
Temuan utama menunjukkan bahwa adaptasi Gereja memerlukan pembaruan teologi kontekstual, katekese digital, dan keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial digital, menegaskan relevansi misi Gereja dalam mewujudkan kesejahteraan bersama di tengah disrupsi teknologi.
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang: Transformasi Sosial dan Tantangan Gereja di Era Digital
Dunia saat ini berada dalam fase perubahan fundamental yang signifikan, didorong oleh kemajuan teknologi digital yang pesat. Transformasi ini telah melahirkan apa yang dikenal sebagai “masyarakat digital”.1 Perubahan ini tidak hanya terbatas pada cara individu berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga merombak struktur sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh.1 Fenomena ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, mulai dari lingkungan rumah tangga, tempat kerja, hingga ranah pendidikan dan rekreasi.1
Bagi Gereja, era digital menghadirkan serangkaian tantangan sekaligus peluang yang unik dalam menjalankan misi dan panggilannya.2 Gereja dituntut untuk beradaptasi agar tetap relevan di tengah pergeseran perilaku, gaya hidup, dan kebutuhan spiritual jemaat yang semakin terdigitalisasi.4 Perubahan ini bukan sekadar penambahan layanan daring, melainkan menuntut evaluasi ulang mendasar tentang bagaimana Gereja memahami dan melaksanakan misinya dalam dunia yang dimediasi secara digital.
Ini menunjukkan sebuah pergeseran paradigma dari sekadar merespons alat digital menjadi mengintegrasikan realitas digital ke dalam identitas dan misi intinya. Hal ini memerlukan peninjauan kembali secara teologis mengenai kehadiran, komunitas, dan misi dalam ruang digital yang non-fisik, sangat terhubung, namun seringkali terfragmentasi. Pergeseran ini mengarah pada model kehadiran yang lebih cair, hibrida, dan saling terhubung secara global, yang pada gilirannya menuntut redefinisi konsep “komunitas” dan “kepemilikan” di dalam Gereja.
B. Pentingnya Keterlibatan Gereja dalam Masyarakat Kontemporer
Gereja, baik secara historis maupun teologis, dipanggil untuk terlibat aktif dalam dunia, bukan untuk mengisolasi diri.6 Keterlibatan ini mencakup dimensi spiritual dan sosial, dengan tujuan utama mewujudkan nilai-nilai Injil dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.8
Konsep Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM) secara eksplisit menekankan upaya Gereja untuk terlibat secara holistik dalam kehidupan masyarakat—mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik—demi tercapainya kesejahteraan bersama. Ini adalah perwujudan praktis dari keyakinan teologis yang mendalam bahwa Allah peduli terhadap keseluruhan kehidupan manusia dan ciptaan. Keterlibatan ini melampaui fokus sempit pada keselamatan individu untuk mencakup transformasi masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa misi Gereja secara inheren bersifat publik dan transformatif, mencerminkan kerinduan Allah akan keadilan, perdamaian, dan kemakmuran di semua bidang kehidupan.
C. Tujuan dan Struktur Tulisan
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah dan mendalam bagaimana Gereja dapat menjadi Gereja yang relevan dan berdampak di era digital, dengan landasan teologis yang kuat dan integrasi konsep GGM.
Struktur penulisan akan meliputi definisi Gereja dan Masyarakat, peran dan tujuan Gereja, landasan teologis keterlibatan, karakteristik masyarakat digital, strategi Gereja di era digital, implementasi GGM, serta kesimpulan dan rekomendasi.
II. Memahami Gereja dan Masyarakat
A. Hakikat Gereja: Perspektif Etimologis, Teologis, Sosiologis, dan Institusional
Memahami hakikat Gereja memerlukan peninjauan dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi:
- Etimologis: Kata “gereja” berasal dari bahasa Portugis “Igreja”, yang memiliki kaitan erat dengan “ecclesia” dalam bahasa Latin dan “ekklesia” dalam bahasa Yunani.9 Secara harfiah, “ekklesia” berarti “dipanggil keluar”, merujuk pada persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia menuju terang Kristus.4 Dalam Perjanjian Lama, istilah Ibrani “qahal YHWH” juga menunjuk pada umat yang dipanggil oleh firman Allah untuk menjadi milik-Nya.9 Kata Yunani
Kyriake (κυριακη), yang berarti “dimiliki Tuhan”, juga menekankan kenyataan bahwa Gereja adalah milik Tuhan.9 - Teologis: Dari perspektif teologis, Gereja adalah persekutuan orang yang percaya akan Kristus, umat Allah dari perjanjian baru, dan komunitas di dunia dari Tuhan yang dimuliakan.9 Ini adalah konsep yang memiliki banyak sisi, kadang disebut “Gereja Allah” atau “jemaat Allah”.9 Dalam teologi sistematis, Gereja memiliki tiga segi penting: objektif (sebagai tempat keselamatan), subjektif (sebagai persekutuan orang percaya), dan apostoler/ekstravert (sebagai jembatan antara Allah dan dunia).4 Rasul Paulus dikenal sebagai teolog yang banyak menggunakan kata “gereja” dalam surat-suratnya, menunjukkan pentingnya konsep ini dalam pemikirannya.10
- Sosiologis dan Institusional: Gereja juga dapat dipahami sebagai suatu lembaga atau institusi yang berfungsi sebagai sarana penyalur keselamatan yang diberikan Allah.9 Sebagai sebuah institusi, Gereja memiliki ciri otoritas hierarkis dan kekuasaan yuridis sosial yang memungkinkannya mengatur anggotanya.9 Namun, penting untuk diingat bahwa Gereja juga merupakan komunitas atau organisme, yaitu kumpulan pribadi umat Kristen yang hidup dan berinteraksi.4
Dinamika antara identitas spiritual dan struktur sosial Gereja sangat penting untuk dipahami. Aspek “dipanggil keluar” dan “persekutuan orang percaya” menekankan identitas spiritual, organik, dan relasional Gereja. Sementara itu, aspek “institusi” dan “hierarki” menunjuk pada entitas yang terstruktur, terorganisir, dan terlihat. Terdapat ketegangan atau interaksi dinamis antara keduanya: esensi spiritual (ekklesia sebagai “umat Allah”) adalah alasan keberadaan Gereja, sedangkan struktur institusional adalah sarana operasionalnya di dunia. Terkadang, aspek institusional dapat membayangi aspek organik, atau sebaliknya.
Dualitas ini krusial dalam memahami bagaimana Gereja menavigasi perubahan eksternal seperti era digital; inti spiritualnya memberikan kesinambungan, sementara bentuk institusionalnya harus beradaptasi. Ini menunjukkan bahwa agar Gereja dapat terlibat secara efektif dengan dunia digital, ia harus menyeimbangkan pelestarian identitas spiritual intinya (sebagai komunitas “milik Tuhan” 9) dengan adaptasi struktur organisasi dan operasionalnya (sebagai “institusi” 9) terhadap realitas digital baru. Kegagalan dalam menyeimbangkan ini dapat menyebabkan ketidakrelevanan (jika terlalu kaku) atau kehilangan identitas (jika terlalu cair).
B. Definisi Masyarakat: Konsep Sosiologis dan Unsur-unsurnya
Masyarakat merupakan konsep fundamental dalam sosiologi, yang dapat didefinisikan dari beberapa perspektif:
- Definisi Umum: Secara sederhana, masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama.11 Kelompok ini telah membentuk tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.12 Terbentuknya masyarakat didasari oleh penggunaan perasaan, pikiran, dan keinginan manusia dalam merespons lingkungannya.11
- Perspektif Sosiologis: Sosiologi sendiri adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia, yang berfokus pada perilaku sosial, pola hubungan sosial, interaksi sosial, dan berbagai aspek budaya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.13 Menurut Koentjaraningrat, masyarakat dipahami sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi.14 Selo Soemarjan menambahkan bahwa masyarakat juga merupakan entitas yang menghasilkan kebudayaan, yang lahir dari proses berpikir manusia dan diyakini sebagai nilai-nilai hidup.14
- Unsur-unsur Masyarakat: Ada beberapa unsur yang membentuk suatu masyarakat 14:
- Menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.
- Beranggotakan paling sedikit dua orang atau lebih.
- Berhubungan dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan individu baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antaranggota masyarakat.
- Seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan.
Masyarakat sebagai entitas dinamis dan pembentuk realitas menunjukkan bahwa penekanan pada interaksi, kepentingan bersama, norma, dan budaya mengindikasikan bahwa masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah sistem dinamis tempat makna, nilai, dan bahkan realitas dikonstruksi secara bersama. Pernyataan bahwa “masyarakat dan kebudayaan enggak akan mungkin terpisah karena masyarakat merupakan wadah kebudayaan itu sendiri” 14 merupakan poin krusial. Jika masyarakat adalah entitas dinamis yang menciptakan dan mempertahankan budaya serta nilai-nilai, maka perubahan dalam masyarakat (seperti transformasi digital) akan secara fundamental mengubah realitas yang dibangun bersama ini. Ini berarti Gereja, dalam keterlibatannya dengan masyarakat, tidak berinteraksi dengan latar belakang yang statis, melainkan dengan lanskap makna dan interaksi yang terus berkembang. Sifat dinamis masyarakat ini menyiratkan bahwa misi Gereja bukan hanya untuk memengaruhi masyarakat, tetapi juga untuk memahami dan membedakan realitas baru yang terbentuk di dalamnya. Hal ini memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, terus-menerus mengevaluasi bagaimana pesan Injil dapat dikontekstualisasikan dan dihidupi dalam konstruksi sosial yang terus berkembang ini. Gereja harus menjadi pembelajar sekaligus pengajar dalam konteks ini.
Tabel 1: Perbandingan Definisi Gereja dan Masyarakat
| Aspek | Gereja | Masyarakat |
| Etimologi | Dari Yunani “ekklesia” (dipanggil keluar), Ibrani “qahal YHWH” (umat yang dipanggil), Yunani “Kyriake” (dimiliki Tuhan).4 | Dari Arab “syaraka” (ikut serta), Inggris “society” (interaksi sosial, kebersamaan).14 |
| Hakikat/Definisi | Persekutuan orang percaya akan Kristus, umat Allah perjanjian baru, komunitas Tuhan yang dimuliakan.9 Dapat berupa institusi, organisasi, atau organisme umat Kristen.4 | Sekumpulan individu yang hidup bersama, saling berinteraksi, memiliki kepentingan sama, tatanan kehidupan, norma, dan adat.11 Studi ilmiah tentang perilaku sosial, pola hubungan, interaksi, dan budaya.13 |
| Tujuan/Fungsi | Mengantar keselamatan, melakukan pengajaran yang benar, mewujudkan Kerajaan Allah, menjadi jembatan antara Allah dan dunia.4 | Fungsi interaksi (koordinasi unit sistem sosial), pemeliharaan (mempertahankan prinsip tertinggi), mencapai tujuan (penyusunan skala prioritas).14 |
| Ciri Khas | Memiliki otoritas hierarkis, kekuasaan yuridis sosial.9 Bersifat spiritual (tidak tampak) namun juga institusional (terlihat).9 | Menghasilkan kebudayaan, beranggotakan minimal dua orang, berhubungan dalam waktu lama, sadar sebagai satu kesatuan.14 |
C. Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM): Fondasi Keterlibatan Holistik
Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM) merupakan konsep yang sangat relevan dalam memahami peran Gereja di tengah dinamika sosial. GGM secara spesifik merujuk pada upaya Gereja untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan politik . Tujuan utama dari GGM adalah mewujudkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.
GGM memiliki beberapa poin penting yang menjadi fokus keterlibatannya :
- Keterlibatan Sosial: Gereja terpanggil untuk peka dan responsif terhadap isu-isu sosial yang ada di masyarakat.
- Kesejahteraan Bersama: Upaya Gereja diarahkan untuk menciptakan kondisi di mana semua anggota masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak dan sejahtera.
- Pelayanan dan Kesaksian: Keterlibatan Gereja merupakan wujud nyata dari pelayanan kasih Allah dan kesaksian akan Injil melalui tindakan konkret.
- Kerja Sama Lintas Sektor: Gereja didorong untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lain, untuk mencapai tujuan bersama.
- Pendidikan dan Pemberdayaan: Gereja berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat melalui program pendidikan dan pemberdayaan.
- Peran Ganda Gereja: Gereja menjalankan peran sebagai komunitas spiritual sekaligus agen perubahan sosial.
Contoh-contoh konkret implementasi GGM mencakup :
- Pelayanan Kesehatan: Melalui rumah sakit, klinik, atau program kesehatan komunitas yang dikelola Gereja.
- Program Pendidikan: Pendirian sekolah, beasiswa, atau program literasi untuk masyarakat.
- Advokasi Kebijakan: Mengangkat suara untuk keadilan sosial dan hak-hak kelompok rentan di ranah publik.
- Pemberdayaan Ekonomi: Melalui pelatihan keterampilan, koperasi, atau dukungan bagi usaha mikro masyarakat.
- Pelayanan Sosial: Bantuan bencana, panti asuhan, panti jompo, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya.
GGM sebagai perwujudan teologi inkarnasional dan misi holistik menunjukkan bahwa konsep ini selaras langsung dengan Missio Dei (misi Allah) dan inkarnasi Kristus. Yesus tidak hanya memberitakan Injil; Ia menyembuhkan, memberi makan, menantang norma-norma sosial, dan terlibat dengan realitas politik pada zamannya.6 Kehidupan-Nya adalah demonstrasi holistik Kerajaan Allah. GGM bukan sekadar kerangka strategis; ini adalah perwujudan praktis dari keyakinan teologis yang mendalam bahwa Allah peduli terhadap keseluruhan kehidupan manusia dan ciptaan.
Ini bergerak melampaui fokus sempit pada keselamatan individu untuk mencakup transformasi masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa misi Gereja secara inheren bersifat publik dan transformatif, mencerminkan kerinduan Allah akan keadilan, perdamaian, dan kemakmuran di semua bidang kehidupan. Penekanan kuat pada GGM berarti Gereja tidak dapat menarik diri ke dalam urusan spiritual atau internal semata di era digital. Sebaliknya, Gereja harus menemukan cara-cara baru untuk memperluas misi holistiknya ke dalam ruang digital, mengatasi ketidaksetaraan digital, mengadvokasi keadilan digital, dan mendorong kesejahteraan digital, sama seperti yang dilakukannya di komunitas fisik. Hal ini menuntut pengembangan “diakonia digital” dan “marturia digital” yang sama kuatnya dengan rekan-rekan tradisionalnya.
III. Peran dan Tujuan Gereja dalam Masyarakat
A. Mandat Alkitabiah: Gereja sebagai Garam dan Terang Dunia (Matius 5:13-16)
Yesus secara tegas menyatakan identitas dan panggilan pengikut-Nya sebagai “garam dunia” (Matius 5:13) dan “terang dunia” (Matius 5:14).15 Ini adalah fondasi misi Gereja di tengah masyarakat.
- Garam Dunia: Sebagai “garam dunia”, orang Kristen dipanggil untuk memberikan pengaruh positif yang mencegah kebusukan moral dan sosial, serta menghidupi nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah dunia yang cenderung “tawar” atau kehilangan arah.15 Keasinan ini diwujudkan melalui cara hidup yang berbeda, keputusan yang diambil, penggunaan sumber daya (seperti uang), dan interaksi sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai ilahi, bukan nilai-nilai duniawi.16 Peringatan Yesus sangat jelas: jika garam itu menjadi tawar, ia tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang.15 Ini menunjukkan bahwa kompromi dengan nilai-nilai dunia akan menghilangkan efektivitas kesaksian Gereja.
- Terang Dunia: Yesus mengasumsikan bahwa dunia, dengan segala kemajuan dan budayanya, berada dalam kegelapan spiritual dan moral.16 Dalam kegelapan ini, manusia seringkali tidak menyadari kebutuhan mereka akan keselamatan dari Tuhan dan hidup yang menyenangkan Dia.16 Gereja, sebagai “terang dunia”, dipanggil untuk menunjukkan Yesus melalui perbuatan baik dan kehidupan yang memuliakan Tuhan.16 Terang ini tidak boleh disembunyikan, melainkan harus diletakkan di atas kaki dian agar menerangi semua orang di dalam rumah.16
Konsep garam dan terang sebagai identitas misioner yang implisit dan eksplisit menunjukkan adanya dua dimensi penting dalam kesaksian Kristen. “Garam” menyiratkan agen pengawet dan pemberi rasa, yang seringkali bekerja secara halus, implisit, dan meresap dalam konteks yang lebih besar. “Terang” menyiratkan visibilitas, bimbingan, dan pewahyuan, yang seringkali lebih eksplisit. Ini menunjukkan sifat ganda kesaksian Kristen: pengaruh implisit melalui karakter dan nilai-nilai (garam) dan proklamasi serta demonstrasi eksplisit kebenaran dan kasih Allah (terang). Efektivitas “garam” terletak pada kehadirannya dan pengaruhnya yang meresap, sementara “terang” adalah tentang visibilitas dan arah yang jelas. Keduanya sangat penting. Di era digital, dualitas ini menjadi semakin krusial. Aspek “garam” berarti orang Kristen harus mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam interaksi digital mereka (misalnya, menghindari ujaran kebencian, mempromosikan kebenaran 2), bahkan dalam aktivitas online yang tampaknya biasa. Aspek “terang” berarti secara aktif menggunakan platform digital untuk penginjilan, pendidikan, dan advokasi sosial 3, membuat Injil terlihat dan mudah diakses. Tantangannya adalah memastikan “garam” tidak kehilangan rasanya (kompromi dengan keburukan digital) dan “terang” tidak tersembunyi (mundur dari keterlibatan digital).
B. Tiga Tugas Panggilan Gereja: Koinonia, Marturia, dan Diakonia
Misi Gereja diwujudkan melalui tiga tugas panggilan yang bersifat integral dan saling terkait:
- Koinonia (Persekutuan): Tugas ini berfokus pada pemeliharaan persekutuan umat untuk meningkatkan iman dan pengabdian kepada Yesus Kristus, serta memperjuangkan persatuan umat Kristen, baik secara denominasional maupun interdenominasional.18 Koinonia terwujud dalam berbagai kegiatan seperti Pendalaman Iman (PA), bergabung dalam kelompok muda-mudi Gereja, atau perkumpulan lingkungan.18 Tujuannya adalah mempererat tali persaudaraan dan menampakkan kehadiran Yesus Kristus di antara umat.18
- Marturia (Kesaksian/Pewartaan): Marturia adalah tugas pemberitaan Injil kepada semua makhluk.18 Ini mencakup proklamasi Injil keselamatan dan kemerdekaan manusia dari belenggu dosa.19 Selain itu, marturia juga berarti kesaksian Injil dalam konteks pelayanan terpadu yang menyentuh semua aspek kebutuhan hidup manusia—tubuh, jiwa, dan roh.19 Contoh praktisnya adalah katekese bagi calon baptis, pelayanan sakramen, dan membantu umat mendalami Firman Allah agar hidup kekal dan setia pada ajaran Tuhan Yesus.18
- Diakonia (Pelayanan Sosial): Tugas diakonia adalah mewujudkan kasih Allah kepada manusia pada umumnya, baik di dalam maupun di luar Gereja.18 Ini melibatkan kegiatan konkret seperti membantu korban bencana alam, mengikuti kegiatan amal bagi mereka yang miskin, cacat, atau terlantar, serta hidup bersama orang yang menderita.18 Semua tindakan diakonia harus dilandasi oleh sikap empati, kepedulian, dan keikhlasan demi kepentingan seluruh umat manusia.18 Gereja juga berperan penting dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui pelayanan diakonia.8
Interdependensi trinitas misi Gereja dalam konteks sosial menunjukkan bahwa ketiga tugas ini, meskipun sering dibahas secara terpisah, memiliki hubungan sinergis. Koinonia (persekutuan internal) memberikan kekuatan dan identitas untuk Marturia (kesaksian eksternal) dan Diakonia (pelayanan sosial). Marturia memberikan tujuan dan arah bagi Koinonia dan Diakonia. Diakonia menunjukkan kasih yang mendasari Koinonia dan Marturia, menjadikannya kredibel. Ini bukan daftar hierarkis, melainkan trinitas yang saling bergantung. Komunitas internal yang kuat (koinonia) mendorong kesaksian yang kredibel (marturia) dan pelayanan yang penuh kasih (diakonia).
Sebaliknya, pelayanan dan kesaksian yang tulus menarik orang ke dalam persekutuan. Mengabaikan salah satu akan melemahkan yang lain. Di era digital, interdependensi ini sangat krusial. Koinonia digital (komunitas online, persekutuan virtual) harus cukup kuat untuk mendukung marturia digital (penginjilan online, kehadiran digital yang etis) dan diakonia digital (advokasi keadilan digital, kelompok dukungan online).
Tantangannya adalah memastikan platform digital tidak menumbuhkan “konsumen spiritual” yang terisolasi, melainkan “pelayan yang bersaksi” yang saling terhubung. Gereja harus secara sengaja merancang ruang digital yang menumbuhkan komunitas, kesaksian, dan pelayanan yang otentik dan saling bergantung.
C. Tujuan Gereja Bermasyarakat: Mewujudkan Nilai-nilai Injil dan Kesejahteraan Bersama
Tujuan utama Gereja bermasyarakat adalah mewujudkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan . Ini selaras dengan panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia, yang tidak hanya memengaruhi individu tetapi juga tatanan sosial.15
Gereja dipanggil untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi guna mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat di sekitarnya.20 Peran ini menjadi semakin krusial di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang dapat memperlemah kohesi sosial.8 Gereja seringkali berfungsi sebagai mediator dalam upaya rekonsiliasi, serta menjadi tempat di mana masyarakat dapat belajar tentang pentingnya hidup berdampingan dengan damai di tengah keberagaman budaya, etnis, dan agama.8 Selain itu, Gereja juga berperan aktif dalam bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, melalui pelayanan diakonia yang memfasilitasi anggota Gereja untuk berbaur dan membangun komunitas di masyarakat.8
Pergeseran dari kesejahteraan spiritual ke kesejahteraan holistik (flourishing) menunjukkan bahwa tujuan Gereja adalah “mewujudkan nilai-nilai Injil” dan “berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat” . Berbagai referensi juga menyebutkan keadilan, perdamaian, pendidikan, dan kesehatan.8 “Kesejahteraan masyarakat” melampaui sekadar kesejahteraan spiritual. Ini mencakup dimensi fisik, sosial, ekonomi, dan moral. Hal ini selaras dengan konsep shalom dalam teologi biblika, yang merujuk pada perdamaian komprehensif, keutuhan, dan kemakmuran. Tujuan Gereja bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa bagi kehidupan setelah mati, tetapi untuk mendorong kemakmuran di dunia ini, mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah di bumi. Ini menyiratkan komitmen untuk mengatasi ketidakadilan sistemik, mempromosikan martabat manusia, dan merawat ciptaan.
Di era digital, ini berarti misi Gereja meluas untuk mempromosikan “shalom digital”. Ini termasuk mengadvokasi akses digital yang adil, memerangi bahaya online (disinformasi, perundungan siber 2), mendorong identitas digital yang sehat, dan menggunakan teknologi untuk memberdayakan kaum marjinal. Gereja harus melihat ruang digital bukan hanya sebagai alat untuk penginjilan, tetapi sebagai ladang misi baru di mana kesejahteraan holistik perlu dikejar.
IV. Landasan Teologis Keterlibatan Gereja dalam Masyarakat
A. Perspektif Teolog dan Filsuf Kristen tentang Keadilan Sosial dan Pelayanan
Keterlibatan Gereja dalam masyarakat memiliki landasan teologis yang kuat, didukung oleh ajaran Alkitab serta pemikiran para teolog dan filsuf Kristen terkemuka:
- Perjanjian Lama: Tuhan memerintahkan umat-Nya untuk menolong orang miskin (Ulangan 15:11) dan membebaskan yang teraniaya (Yesaya 58:6-7).6 Menindas orang lemah dianggap menghina Pencipta (Amsal 14:31) 6, menunjukkan bahwa keadilan sosial adalah bagian dari karakter ilahi.
- Perjanjian Baru: Yesus sendiri dalam perumpamaan-Nya (Matius 25:42-45) menyamakan tindakan menolong yang lapar, haus, asing, telanjang, sakit, atau di penjara dengan melayani Dia sendiri.6 Ini menegaskan bahwa pelayanan sosial adalah pelayanan kepada Kristus. Sikap saling mengasihi adalah hukum dasar kehidupan orang percaya.6 Rasul Paulus dalam Roma 13:1-7 menekankan ketaatan kepada pemerintah sebagai kehendak Allah, namun ketaatan ini bukanlah penyerahan diri membabi buta, melainkan ketaatan yang kritis dan bertanggung jawab.19
- Timothy Keller: Mengemukakan bahwa perintah Allah dalam Alkitab merupakan alat pembebasan yang memanggil manusia kembali kepada tujuan penciptaan mereka.6 Ini berarti ketaatan pada perintah ilahi membawa pada pemulihan dan kemakmuran.
- John Stott: Berpendapat bahwa di mana pun orang Kristen bertindak sebagai terang dan garam, kemerosotan sosial akan surut dan kesejahteraan sosial akan meningkat.6 Ini menegaskan dampak transformatif kehadiran Kristen dalam masyarakat.
- Martin Luther King Jr.: Seorang pemimpin hak sipil dan pendeta, mendasarkan pandangannya tentang pembangunan kesejahteraan masyarakat pada prinsip pelayanan dan pengampunan, yang menginspirasi gerakan hak sipil non-kekerasan yang masif.7
- Richard Niebuhr: Seorang teolog dan filsuf, mengemukakan bahwa Kekristenan memegang prinsip bahwa manusia rentan terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, Gereja memiliki tanggung jawab untuk berdiri di sisi yang lemah dan memperjuangkan keadilan sosial dalam masyarakat. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan masyarakat dalam merespons kesenjangan dan ketidakadilan.7
- Max Weber: Menganalisis kaitan antara etika Protestan dan perubahan sosial. Ia melihat kerja sebagai panggilan hidup yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi sebagai tugas suci. Weber berpendapat bahwa Gereja dan orang Kristen harus mampu menciptakan perubahan sosial dan berkolaborasi dengan birokrasi pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial.21 Ia menekankan rasionalitas instrumental dalam mencapai tujuan sosial.21
- Webber (pemikir Kristen): Menekankan bahwa Gereja dan orang Kristen harus mampu menciptakan perubahan sosial, turun langsung ke lapangan untuk melihat persoalan, dan memberikan sumbangsih untuk meringankan beban pemerintah. Ini termasuk kerjasama antar-gereja untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan ekonomi, dan pendidikan.21
Kumpulan teks alkitabiah dan pandangan teolog ini secara konsisten menghubungkan iman Kristen dengan keadilan sosial, kepedulian terhadap kaum miskin, dan kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya tentang amal; ini tentang keadilan. Penekanan berulang pada “menolong orang miskin,” “membebaskan yang teraniaya,” “keadilan sosial,” dan “tidak menindas” menunjuk pada pemahaman teologis tentang karakter Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Metafora “garam dan terang,” ketika diterapkan pada masyarakat, menyiratkan transformasi struktur sosial, bukan hanya kehidupan individu.
Keterlibatan dalam isu-isu sosial berasal dari sifat Allah sendiri dan perintah-Nya, bukan sekadar tambahan opsional pada iman. Ini adalah sebuah keharusan yang berakar pada karakter Allah (yang adil) dan teladan Kristus (yang melayani secara holistik). Dengan demikian, tindakan sosial adalah tindakan ibadah dan ketaatan. Di era digital, keharusan teologis ini menuntut Gereja tidak hanya mengatasi bahaya online tetapi juga secara aktif memperjuangkan keadilan digital. Ini termasuk mengadvokasi literasi digital untuk semua, memastikan akses yang adil terhadap teknologi, memerangi bias algoritmik, dan menantang sistem digital yang melanggengkan ketidaksetaraan atau eksploitasi.
Sikap teologis Gereja tentang keadilan harus meluas ke ranah digital, menjadi suara kenabian dalam etika AI, privasi data, dan kesenjangan digital.
Tabel 2: Landasan Teologis Keterlibatan Gereja dalam Masyarakat
| Sumber/Pemikir | Konsep Kunci | Relevansi dengan Keterlibatan Sosial |
| Alkitab Perjanjian Lama | Ulangan 15:11, Yesaya 58:6-7, Amsal 14:31 | Perintah menolong orang miskin, membebaskan yang teraniaya, menegaskan keadilan sebagai karakter ilahi.6 |
| Alkitab Perjanjian Baru | Matius 5:13-16 (Garam & Terang), Matius 25:42-45 (Pelayanan kepada yang hina), Roma 13:1-7 (Ketaatan kritis pada pemerintah), Yeremia 29:7 (Kesejahteraan kota) | Identitas misioner Gereja, pelayanan kepada yang membutuhkan sebagai pelayanan kepada Kristus, tanggung jawab warga negara Kristen, doa dan upaya bagi kesejahteraan kota.6 |
| Timothy Keller | Perintah Allah sebagai alat pembebasan | Ketaatan pada kehendak Allah membawa pada pemulihan dan kemakmuran manusia.6 |
| John Stott | Garam & Terang mengurangi kemerosotan sosial | Kehadiran Kristen yang otentik membawa dampak transformatif pada masyarakat.6 |
| Martin Luther King Jr. | Prinsip pelayanan dan pengampunan | Mendorong gerakan keadilan sosial non-kekerasan, berpusat pada kasih dan rekonsiliasi.7 |
| Richard Niebuhr | Manusia rentan ketidakadilan, gereja membela yang lemah | Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan sosial dan merespons kesenjangan.7 |
| Max Weber | Etika Protestan dan perubahan sosial, rasionalitas instrumental | Kerja sebagai panggilan suci, kolaborasi gereja-pemerintah untuk keadilan sosial.21 |
| Webber (pemikir Kristen) | Gereja menciptakan perubahan sosial | Keterlibatan langsung di lapangan, bakti sosial, program gratis, kerjasama antar-gereja untuk kesejahteraan.21 |
| Konsep Teologis Utama | Inkarnasi Kristus, Missio Dei, Imago Dei, Koinonia, Marturia, Diakonia | Allah terlibat dalam realitas manusia, Gereja sebagai instrumen misi penebusan Allah, manusia sebagai agen Allah untuk mengolah dunia, tugas integral Gereja.4 |
B. Inkarnasi Kristus sebagai Model Keterlibatan dan Solidaritas Gereja
Landasan teologis yang sangat kuat bagi keterlibatan Gereja dalam masyarakat adalah konsep inkarnasi Kristus. Inkarnasi merujuk pada peristiwa di mana Yesus Kristus, yang adalah Allah, menjelma menjadi manusia seutuhnya, tinggal bersama manusia, dan terlibat secara mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk struktur sosial, ekonomi, dan politik pada zamannya.6 Ini adalah alasan kuat bagi Gereja untuk tidak mengisolasi diri dari dunia.
Gereja dipanggil untuk melanjutkan inkarnasi kasih Allah ini. Artinya, Gereja harus meneladani Kristus dengan melibatkan diri dalam masalah-masalah dunia, memberikan pengharapan kepada mereka yang tertindas, miskin, dan tereksploitasi.6 Kehadiran Kristus yang memindahkan umat ke dalam kerajaan kasih-Nya harus termanifestasi dalam tindakan pelayanan yang nyata di tengah masyarakat.19
Inkarnasi sebagai paradigma untuk kehadiran digital yang otentik menunjukkan bahwa jika Gereja ingin mengikuti model inkarnasional ini di era digital, ia tidak bisa hanya menyiarkan pesan ke dunia digital; ia harus hadir di dalam dunia digital. Ini berarti mengembangkan kehadiran digital yang otentik, terlibat dalam hubungan digital yang tulus, dan mewujudkan nilai-nilai Kristen dalam ruang digital yang seringkali impersonal. Ini menantang gagasan “virtual” sebagai “tidak nyata” 23, dengan argumen bahwa Allah dapat memanifestasikan kehadiran-Nya bahkan melalui pengalaman yang dimediasi.23
Hal ini menyiratkan panggilan untuk “inkarnasi digital” – kesediaan Gereja untuk mewujudkan kehadiran dan nilai-nilai Kristus dalam alam virtual. Ini krusial bagi eklesiologi digital 23, yang menunjukkan bahwa ibadah online, komunitas, dan pelayanan, meskipun berbeda dari fisik, tetap dapat menjadi ekspresi otentik Gereja, asalkan secara tulus mencerminkan prinsip inkarnasional dari keterlibatan yang mendalam dan empatik. Ini juga menantang Gereja untuk mempertimbangkan bagaimana ia dapat membuat Imago Dei terlihat dalam dunia yang semakin bergulat dengan identitas digital dan ideologi transhumanis.23
C. Imago Dei dan Missio Dei: Landasan Misi Sosial Gereja
Dua konsep teologis fundamental yang menjadi landasan kuat bagi misi sosial Gereja adalah Imago Dei (Gambar Allah) dan Missio Dei (Misi Allah).
- Missio Dei: Ini adalah konsep yang merujuk pada aktivitas Allah Tritunggal untuk menebus ciptaan-Nya dari kehancuran akibat dosa.22 Gereja dipandang sebagai instrumen istimewa yang dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi penebusan dan penciptaan kembali manusia dan kosmos oleh Allah.23 Misi Allah adalah inti dari Alkitab, yang menyajikan pandangan dunia Allah dan keterlibatan-Nya di dunia, menghasilkan dan mendukung identitas serta orientasi Kristen.23
- Imago Dei: Konsep ini menjelaskan bahwa identitas manusia diciptakan sesuai dengan identitas yang diberikan Allah, dengan peran teologis yang unik sebagai wakil dan cerminan ilahi di bumi.23 Mandat budaya yang diberikan Allah kepada manusia dalam Kejadian 1:27-28, yaitu untuk mengolah dan memelihara dunia nyata, secara intrinsik mengikat Imago Dei dengan Missio Dei.23 Ini menjadikan manusia sebagai agen Allah dalam mewujudkan kehendak-Nya di dunia.
Keterkaitan antara hakikat manusia dan misi transformatif Gereja sangat mendalam. Missio Dei adalah misi penebusan Allah, dan Imago Dei adalah identitas manusia sebagai pembawa gambar Allah, yang terkait dengan mandat budaya.23 Hubungan antara Imago Dei dan Missio Dei sangatlah mendalam. Manusia bukan hanya penerima pasif keselamatan, melainkan peserta aktif dalam karya penebusan dan penciptaan Allah yang berkelanjutan.
Sifat dasar kita sebagai pembawa gambar Allah mendorong kita untuk terlibat dan mengubah dunia. Ini membangun hubungan kausal yang fundamental: karena manusia diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei), mereka secara inheren diperintahkan untuk berpartisipasi dalam misi Allah (Missio Dei) untuk mengolah dan merawat ciptaan, yang mencakup ranah sosial, ekonomi, dan politik. Ini berarti tindakan sosial bukanlah tambahan opsional, melainkan bagian intrinsik dari makna menjadi manusia dan mengikuti Allah. Di era digital, ini berarti misi Gereja meluas untuk menegaskan dan melindungi Imago Dei dalam konteks digital.
Ini melibatkan penantangan aspek-aspek budaya digital yang merendahkan martabat manusia (misalnya, manipulasi identitas, kejahatan siber 23), mempromosikan martabat digital, dan memastikan teknologi melayani kemakmuran manusia daripada merendahkannya. Gereja harus mengartikulasikan antropologi (pemahaman tentang kemanusiaan) yang kuat yang melawan ideologi transhumanis dan cyborg yang mungkin berusaha mendefinisikan ulang sifat manusia terlepas dari rancangan Allah.23
V. Masyarakat Digital: Karakteristik dan Dampaknya
A. Definisi dan Ontologi Masyarakat Digital (Cyberspace)
Masyarakat digital adalah sebuah realitas yang semakin dominan di era kontemporer, yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik dan ontologinya.
- Masyarakat Digital: Ini adalah masyarakat progresif yang terbentuk melalui adaptasi dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengetahuan komputer, dan humaniora.1 Integrasi ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari rumah, tempat kerja, pendidikan, hingga rekreasi, di mana teknologi digital dimanfaatkan secara otomatis melalui sistem terkomputerisasi.1 Teknologi digital memproses informasi sebagai nilai numerik (kode digital) dengan kecepatan tinggi, berbeda dengan kerja manual manusia.1
- Cyberspace: Konsep cyberspace adalah kunci untuk memahami masyarakat digital. Cyberspace didefinisikan sebagai “ruang imajiner” di mana individu dapat melakukan segala aktivitas sosial sehari-hari secara artifisial, yaitu melalui teknologi komputer dan informasi.25 Di dalam ruang ini, berbagai kegiatan seperti berinteraksi, berdiskusi, berbisnis, bahkan menciptakan karya seni, dapat dilakukan.25 Objek-objek di cyberspace adalah “objek tak nyata” yang ditangkap pengalaman hanya dalam wujud halusinasi, dibentuk oleh satuan informasi (bit/byte), dan tidak mengikuti hukum fisika.25 Sifat cyberspace sebagai dunia yang terbentuk oleh jaringan (web) dan hubungan (connection)—bukan oleh materi—menjadikan kesalingterhubungan (interconnectedness) dan kesalingbergantungan (interdependency) secara virtual sebagai ciri khasnya.25
Realitas ganda dan tantangan ontologis keberadaan muncul dari deskripsi masyarakat digital dan cyberspace. Masyarakat semakin “digital” 1, beroperasi di “cyberspace,” yang digambarkan sebagai “ruang imajiner” di mana aktivitas bersifat “artifisial” dan objeknya “tidak nyata”.25 Istilah “imajiner,” “artifisial,” dan “tidak nyata” ini disandingkan dengan “aktivitas sosial” dan “kehidupan sehari-hari.”
Hal ini menciptakan ketegangan: bagaimana ruang yang “tidak nyata” dapat menjadi tempat interaksi dan aktivitas manusia yang “nyata”? Ini menunjuk pada tantangan ontologis fundamental: era digital memaksa evaluasi ulang tentang apa yang membentuk “realitas” dan “keberadaan.” Manusia kini beroperasi dalam “realitas ganda” – fisik dan virtual – di mana virtual semakin berdampak pada fisik. Aspek “halusinasi” 25 menunjukkan bahwa meskipun pengalaman dirasakan, sifat dasarnya non-fisik, menimbulkan pertanyaan tentang kehadiran dan keberwujudan.
Bagi Gereja, ini berarti pelayanan pastoral, pembangunan komunitas, dan penginjilan harus menghadapi realitas ganda ini. Bagaimana seseorang dapat “hadir” dalam “ruang imajiner”? Bagaimana Gereja melayani individu yang identitasnya semakin terfragmentasi antara diri fisik dan digital?25 Ini menuntut “teologi digital” 26 yang dapat mengartikulasikan kesakralan dan realitas kehadiran Allah serta interaksi manusia dalam lanskap ontologis baru yang kompleks ini.
B. Dampak pada Interaksi Sosial, Komunikasi, dan Identitas
Masyarakat digital secara fundamental mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami identitas mereka:
- Identitas Individu: Cyberspace secara mendasar mengubah pemahaman tentang diri (self) dan identitas (identity).25 Struktur cyberspace memberikan ruang luas bagi setiap orang untuk menciptakan konsep diri dan identitas secara “artifisial” dan tak terbatas. Kondisi ini dapat membuat konsep diri dan identitas menjadi tanpa makna, mengarah pada “kematian perbedaan” (death of difference) atau “permainan identitas” yang mencakup identitas baru, palsu, ganda, atau jamak, yang dalam psikoanalisis disebut “diri terbelah” (divided self).25 Selain itu, komunikasi virtual di cyberspace dapat menciptakan “candu cyber” (cyber-addiction), khususnya “kecanduan komunikasi” (communication addiction), yang membuat individu menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer.25
- Interaksi Antar-individu: Hubungan, relasi, dan interaksi sosial di cyberspace tidak melibatkan fisik di wilayah atau teritorial tertentu, sehingga menciptakan “deteritorialisasi sosial” (social deterritorialisation).25 Ini berarti interaksi sosial tidak lagi terbatas pada teritorial nyata, melainkan dapat terjadi dalam “halusinasi teritorial”, di mana seseorang bisa lebih dekat secara sosial dengan orang yang jauh secara teritorial daripada tetangga dekatnya.25 Bentuk komunikasi sosial di
cyberspace sangat dibentuk oleh peran citra dan sangat rentan terhadap penipuan, pemalsuan, dan simulasi realitas.25 - Tingkat Komunitas: Cyberspace diasumsikan dapat menciptakan model komunitas demokratis dan terbuka yang disebut “komunitas imajiner” (imaginary community).25 Namun, masalah utamanya adalah lemahnya kontrol normatif dan sosial karena tidak adanya lembaga (institution) fisik, yang mengarah pada “demokrasi radikal” atau “hiper-demokrasi” di mana “apapun boleh” (anything goes).25 Ruang ini juga dapat menjadi “ruang publik virtual” yang bebas namun rentan terhadap manipulasi dan kejahatan tersembunyi, seperti cybercrime, cyberviolence, cyberporn, dan cyberanarchy.25
Fragmentasi identitas dan erosi kontrol sosial sebagai ancaman fundamental adalah konsekuensi dari dampak digitalisasi. Ranah digital memengaruhi identitas (“diri terbelah,” “kematian perbedaan”), interaksi sosial (“deteritorialisasi,” berbasis citra, rentan manipulasi), dan komunitas (“imajiner,” “demokrasi radikal,” “apapun boleh,” kejahatan siber).25
Dampak-dampak ini tidak terisolasi; mereka saling terkait. Kemampuan untuk menciptakan banyak identitas (fragmentasi) melemahkan akuntabilitas. Interaksi yang terdeteritorialisasi mengurangi konsekuensi sosial langsung dari perilaku. Kurangnya kontrol institusional dalam “demokrasi radikal” memperparah potensi penyalahgunaan dan manipulasi. Tren yang mendasari adalah fragmentasi identitas dan erosi mekanisme kontrol sosial tradisional. Ini menciptakan lahan subur bagi perpecahan, ketidakpercayaan, dan kemerosotan moral, di mana “kekerasan semiotik” 25 dan “penyederhanaan kebenaran” 27 menjadi lazim. “Insting-insting purba manusia” 25 dilepaskan dalam lingkungan yang kurang terkendali.
Bagi Gereja, ini menimbulkan tantangan mendalam terhadap misinya untuk menumbuhkan identitas holistik, membangun komunitas yang tulus (koinonia), dan mempromosikan kebenaran (marturia). Gereja harus mengembangkan strategi untuk melawan fragmentasi identitas dengan menegaskan Imago Dei dalam diri digital, membangun kembali komunitas otentik melintasi batas fisik dan virtual, dan membekali orang percaya untuk membedakan kebenaran di tengah disinformasi dan “kekerasan semiotik.” Ini memerlukan etika digital 17 yang kuat dan fokus baru pada katekese 3 yang membahas kewarganegaraan digital dan pembedaan moral.
C. Tantangan Etika dan Moralitas di Ruang Digital
Ruang digital, meskipun menawarkan banyak kemudahan, juga menghadirkan tantangan etika dan moralitas yang kompleks bagi individu dan masyarakat, termasuk Gereja:
- Disinformasi dan Hoaks: Media sosial seringkali menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak akurat, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.2 Konten semacam ini dapat menyesatkan umat, memecah belah komunitas, dan bahkan memicu konflik. Pemerintah sendiri berupaya mencegah penyebaran hoaks melalui berbagai imbauan dan tindakan.30
- Krisis Otoritas: Otoritas tradisional, seperti Gereja, pendeta, dan institusi teologi, menghadapi tantangan serius dengan munculnya “teolog amatir” di media sosial.27 Individu-individu ini seringkali mendapatkan pengaruh signifikan karena jumlah pengikut yang besar, meskipun konten mereka mungkin tidak memiliki dasar akademik atau teologis yang kuat. Akibatnya, masyarakat cenderung lebih percaya pada otoritas personal dan populis daripada otoritas institusional.27
- Simplifikasi Kebenaran: Di era digital, refleksi teologis yang mendalam sering dikorbankan demi penyajian konten yang singkat, ringan, dan mudah dikonsumsi.27 Fenomena ini terlihat dalam video khotbah pendek, kutipan inspiratif di media sosial, atau blog yang lebih mengutamakan dampak emosional daripada kedalaman teologis. Konsekuensinya, pemahaman iman yang kompleks dan reflektif seringkali direduksi menjadi slogan atau narasi dangkal.27
- Anti-Sosial dan Individualisme: Kecenderungan anggota Gereja untuk mengandalkan ibadah daring dapat menyebabkan keengganan untuk berpartisipasi dalam persekutuan luring.2 Hal ini berpotensi membuat jemaat menjadi anti-sosial dan meninggalkan persekutuan Gereja yang mendalam, yang merupakan inti dari koinonia.2
- Transhumanisme dan Cyborg: Budaya digital menghadirkan tantangan serius dalam bentuk transhumanisme dan cyborg, yang berpotensi bertentangan dengan iman Kristen.23 Ideologi ini bertujuan untuk secara radikal mengubah makna menjadi manusia melalui teknologi, bahkan mencari keabadian atau “kehidupan sempurna” dengan menghindari penuaan dan meningkatkan efisiensi tubuh.23 Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang “imago Dei” (gambar Allah) versus “imago meta” (identitas buatan manusia di dunia digital).23
- Digital Docetism dan Digital Gnosticism: Era tanpa tubuh (disembodied era) yang dimungkinkan oleh teknologi digital dapat memunculkan bentuk-bentuk teologi yang menyimpang. Digital Docetism adalah pandangan yang menyangkal corporeality atau keberadaan fisik manusia sebagai manusia yang sepenuhnya berwujud. Sementara itu, Digital Gnosticism cenderung meremehkan signifikansi pengalaman fisik manusia dalam kehidupan duniawi sehari-hari.23 Kedua pandangan ini mencerminkan tantangan dalam memahami dimensi spiritual manusia di tengah perkembangan teknologi modern.
Disrupsi epistemologis dan antropologis sebagai ancaman eksistensial adalah isu yang lebih dalam dari tantangan etika digital. Era digital menghadirkan tantangan seperti disinformasi, krisis otoritas, penyederhanaan kebenaran, perilaku anti-sosial, dan bahkan isu yang lebih mendalam seperti transhumanisme serta Digital Docetism/Gnosticism.2 Ini bukan hanya masalah perilaku; ini merupakan disrupsi epistemologis (bagaimana kita mengetahui kebenaran) dan antropologis (apa artinya menjadi manusia). Disinformasi merusak kebenaran itu sendiri. Krisis otoritas mempertanyakan siapa yang mendefinisikan kebenaran. Penyederhanaan kebenaran meremehkan pemahaman teologis yang kompleks. Transhumanisme mendefinisikan ulang kemanusiaan.
Digital Docetism/Gnosticism menantang nilai tubuh fisik dan pengalaman duniawi. Ini merupakan ancaman eksistensial terhadap keyakinan inti Kristen tentang kebenaran, otoritas, sifat manusia, dan nilai ciptaan fisik. Dunia digital bukan hanya media baru; ini adalah medan pertempuran filosofis baru. Gereja harus terlibat dalam teologi filosofis dan apologetika yang kuat di era digital. Ini berarti tidak hanya mengajarkan literasi digital tetapi juga mengembangkan teologi teknologi 26 yang canggih yang dapat mengartikulasikan kebenaran Kristen dalam dunia yang jenuh digital, mempertahankan diri dari distorsi teologis, dan menegaskan kesucian keberwujudan manusia dan ciptaan. Ini menuntut pembekalan orang percaya untuk menjadi warga digital yang cakap yang dapat mengevaluasi informasi secara kritis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen dalam lingkungan online yang ambigu secara moral.
VI. Menjadi Gereja dalam Masyarakat Digital: Tantangan dan Peluang
A. Tantangan Pelayanan Gereja di Era Digital
Menjadi Gereja yang relevan di era digital tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi secara serius:
- Komunikasi Negatif: Salah satu tantangan signifikan adalah kecenderungan anggota Gereja untuk terlibat dalam bentuk komunikasi negatif di media sosial. Ini mencakup ujaran kebencian, fitnah, penyebaran hoaks, dan komunikasi kasar.2 Perilaku semacam ini tidak hanya merusak kesaksian Kristen tetapi juga dapat memecah belah komunitas.
- Anti-Sosial dan Individualisme: Adanya kemudahan akses ibadah daring dapat menyebabkan keengganan anggota Gereja untuk datang bersekutu secara luring.2 Fenomena ini berpotensi membuat jemaat menjadi anti-sosial dan meninggalkan persekutuan Gereja yang mendalam, yang merupakan inti dari koinonia.2 Individualisme yang semakin kuat di era digital dapat mengikis rasa kebersamaan dan tanggung jawab komunal.
- Krisis Identitas dan Teologi yang Terdistorsi: Budaya digital menghadirkan tantangan serius terhadap identitas Kristen. Perkembangan seperti transhumanisme dan cyborg berpotensi bertentangan dengan iman Kristen dengan mengubah hakikat manusia dan mencari keabadian melalui teknologi.23 Ada kekhawatiran yang beralasan bahwa “imago Dei” (identitas yang diberikan Allah) akan menyatu dengan “imago meta” (identitas buatan manusia di dunia digital).23 Selain itu, era tanpa tubuh (disembodied era) dapat memunculkan teologi yang menyimpang seperti Digital Docetism (menyangkal corporeality manusia) atau Digital Gnosticism (meremehkan pengalaman fisik di dunia).23
- Simplifikasi Kebenaran dan Krisis Otoritas: Gereja menghadapi tantangan untuk mempertahankan kedalaman teologis di tengah preferensi konten yang singkat dan mudah dikonsumsi.27 Bersamaan dengan itu, krisis kepercayaan pada otoritas gerejawi tradisional semakin nyata dengan munculnya “teolog amatir” yang memiliki pengaruh besar di media sosial tanpa dasar akademik yang kuat.27
Digitalisasi sebagai katalisator krisis internal Gereja menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini bukan hanya ancaman eksternal bagi Gereja, melainkan seringkali manifestasi internal atau akselerasi dari kelemahan yang sudah ada di dalam Gereja atau anggotanya. Misalnya, individualisme mungkin diperparah oleh ibadah online, atau kurangnya landasan teologis yang mendalam membuat anggota rentan terhadap “teolog amatir.”
Digitalisasi bertindak sebagai katalis yang mengekspos dan mengintensifkan kerentanan internal yang sudah ada di dalam Gereja. Ini tidak menciptakan individualisme atau kedangkalan teologis, tetapi menyediakan jalan baru bagi kecenderungan ini untuk bermanifestasi dan menyebar. Ini menunjukkan bahwa respons Gereja terhadap era digital tidak bisa hanya bersifat teknologi; itu harus sangat pastoral dan formatif. Ini memerlukan penguatan pemuridan internal, pembentukan komunitas yang tulus yang melampaui ruang fisik dan virtual, dan pembekalan anggota dengan pemikiran kritis dan pembedaan teologis untuk menavigasi kompleksitas dunia digital. Fokusnya harus pada pembangunan ketahanan dan kematangan spiritual dalam konteks digital.
B. Peluang dan Strategi Adaptasi Gereja di Ruang Digital
Meskipun menghadapi tantangan, era digital juga membuka peluang besar bagi Gereja untuk memperluas jangkauan pelayanannya dan beradaptasi secara inovatif:
- Pemanfaatan Media Sosial dan Komunikasi Virtual: Gereja dapat secara efektif menggunakan media sosial untuk menjangkau umat yang tersebar di berbagai wilayah, memberikan pembinaan iman daring melalui video, podcast, dan artikel, membangun komunitas digital yang mendukung kehidupan rohani, serta menyediakan sarana konsultasi iman dan pendampingan rohani.5 Pemanfaatan ini juga sangat efektif untuk menyampaikan dan menyebarluaskan berita Injil, khususnya untuk menjangkau generasi Zillennial yang lebih akrab dengan teknologi.22
- Katekese Kontekstual Baru: Gereja perlu merevitalisasi dirinya untuk menemukan metode khotbah dan pengajaran yang baru, serta mempertimbangkan teologi kontekstual yang relevan di era digital.3 Ini mencakup kesadaran untuk melakukan katekese baru yang “mendengarkan dengan hati” untuk pertumbuhan dan perkembangan Gereja sinodal, yang lebih responsif terhadap kebutuhan jemaat.24
- Eklesiologi Misioner Diakronis: Pendekatan misi ini memeriksa perkembangan, evolusi, dan perubahan praktik misi Kristen sepanjang waktu, menekankan keterlibatan aktif dengan komunitas.23 Gereja harus menjadi peserta aktif dalam menanggapi masalah sosial, berkolaborasi untuk membawa perubahan positif, dan memperluas nilai-nilai Kerajaan Allah di dunia masa depan, termasuk di ranah digital.23
- Re-evangelisasi dan Pemuridan: Penting untuk memperkuat pelayanan katekese guna memastikan pertobatan yang benar dan mendalam, bukan hanya sebagai syarat baptisan.33 Gereja perlu melakukan re-evangelisasi dan pemuridan intensif, termasuk melalui pembentukan kelompok sel kecil yang kreatif, untuk membangun jemaat yang bertumbuh secara rohani dan memiliki semangat misioner.33
- Etika Digital: Gereja memiliki peran krusial dalam memberikan pendidikan tentang etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.17 Ini termasuk mengajarkan cara menyaring informasi untuk menghindari hoaks dan berita palsu, serta mempromosikan penggunaan media sosial yang sehat untuk mendukung kehidupan iman, bukan sebagai pengganti keterlibatan langsung dalam komunitas gerejawi.17 Teknologi dipandang baik apabila digunakan untuk memajukan kesejahteraan manusia dan memuliakan Tuhan.28
Inkarnasi digital sebagai strategi misi yang kontekstual dan holistik menunjukkan bahwa peluang-peluang ini secara kolektif mengarah pada “kehadiran digital inkarnasional.” Ini bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tetapi tentang Gereja hadir dan mewujudkan misinya di dalam ruang digital, mirip dengan bagaimana Kristus berinkarnasi ke dalam realitas manusia. Penekanan pada “katekese kontekstual,” “eklesiologi misioner diakronis,” dan “re-evangelisasi” menunjukkan pendekatan holistik yang mengadaptasi cara (metode dan platform) tanpa mengorbankan apa (pesan Injil dan kedalaman teologis).
Ini tentang menjangkau orang di mana pun mereka berada (secara digital) dan terlibat dengan realitas digital mereka, bukan hanya menarik mereka ke ruang fisik. “Inkarnasi digital” ini krusial untuk relevansi dan dampak Gereja. Ini berarti merangkul platform digital sebagai ladang misi yang sah, mengembangkan pelayanan digital yang menumbuhkan komunitas sejati dan pertumbuhan spiritual, dan membekali orang percaya untuk menjadi warga digital yang etis dan efektif. Keberhasilan bergantung pada kesediaan Gereja untuk menjadi rentan, adaptif, dan terlibat secara mendalam dalam kompleksitas dunia digital, mencerminkan keterlibatan Kristus sendiri dengan umat manusia. Ini juga menyiratkan kebutuhan untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital, pelatihan, dan refleksi teologis tentang fenomena digital.
C. Landasan Teologis untuk Gereja Digital: Relevansi Soteriologi, Kristologi, dan Eskatologi
Agar Gereja dapat beroperasi secara efektif dan setia di era digital, landasan teologis yang kokoh sangat diperlukan. Tiga doktrin inti yang relevan adalah Soteriologi, Kristologi, dan Eskatologi:
- Soteriologi (Keselamatan): Gereja digital harus tetap fokus pada misi keselamatan Kristus kepada semua orang.24 Teologi misi berpusat pada
Missio Dei, yaitu aktivitas Allah Tritunggal untuk menebus ciptaan-Nya dari kehancuran akibat dosa.22 Di tengah berbagai tawaran “keselamatan” atau “pembebasan” digital (misalnya, janji keabadian melalui teknologi), Gereja harus dengan jelas menegaskan bahwa keselamatan sejati hanya ditemukan dalam iman kepada Yesus Kristus. - Kristologi (Kristus): Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu, termasuk teknologi dan inovasi digital.23 Oleh karena itu, penggunaan teknologi oleh Gereja harus bertujuan untuk memperluas Kerajaan Allah dan memuliakan-Nya, bukan sebaliknya.23 Inkarnasi Kristus menunjukkan keselarasan sempurna antara media dan pesan, menjadi teladan bagi Gereja untuk “berinkarnasi” ke dalam ruang virtual (misalnya, realitas virtual) untuk tujuan yang sama, yaitu menghadirkan Kristus secara otentik di tengah dunia digital.23 Ini menantang pandangan yang meremehkan keberadaan fisik atau memisahkan pengalaman spiritual dari realitas tubuh.
- Eskatologi (Akhir Zaman): Pesan eskatologis menegaskan bahwa perubahan zaman, termasuk era digital, tidak dapat menggantikan kebenaran Alkitab yang kekal.23 Era digital justru dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan harapan akan Kedatangan Tuhan dan Kerajaan-Nya yang sempurna.23 Ini kontras tajam dengan utopia transhumanis yang mengejar keabadian melalui teknologi dan berambisi menggantikan agama tradisional dengan klaim bahwa teknologi dapat mencapai apa yang telah dicari agama selama ribuan tahun.23
Teologi digital sebagai penjaga kebenaran fundamental di tengah disrupsi antropologis dan eksistensial menunjukkan bahwa doktrin-doktrin teologis inti ini menjadi jangkar dan korektif di era digital.
Era digital menantang pemahaman fundamental tentang keselamatan (misalnya, keselamatan virtual dalam transhumanisme), sifat Kristus (misalnya, teologi tanpa tubuh), dan harapan akhir (misalnya, keabadian digital sebagai utopia). Doktrin-doktrin teologis inti ini menjadi jangkar dan korektif di era digital.
Soteriologi mengingatkan Gereja akan tujuan utamanya (keselamatan dari dosa, bukan hanya kesejahteraan digital). Kristologi menegaskan kedaulatan Kristus atas semua ciptaan, termasuk teknologi, mencegah teknologi menjadi berhala atau penyelamat alternatif. Eskatologi memberikan harapan biblika yang melampaui utopia teknologi, mengakar orang percaya pada rencana akhir Allah daripada fantasi keabadian buatan manusia.
Ini berarti “teologi digital” bukan hanya latihan akademis; itu adalah kebutuhan vital bagi kesetiaan dan kelangsungan hidup Gereja. Gereja harus secara eksplisit mengartikulasikan bagaimana kebenaran Kristen merespons dan mengkritik filosofi yang mendasari dunia digital (misalnya, redefinisi kemanusiaan oleh transhumanisme 23). Gereja harus membekali anggotanya untuk membedakan antara kebenaran biblika dan ilusi digital, memastikan bahwa kemajuan teknologi melayani Kerajaan Allah daripada menggantikannya.
VII. Implementasi Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM) di Era Digital
Integrasi Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM) di era digital menuntut pendekatan yang inovatif dan strategis, memanfaatkan potensi teknologi untuk memperluas dampak pelayanan Gereja.
A. Keterlibatan Sosial dan Kesejahteraan Bersama melalui Platform Digital
Gereja memiliki peran penting dalam mempromosikan keterlibatan sosial dan kesejahteraan bersama di ranah digital. Gereja harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada isu-isu kemanusiaan global dan secara aktif mempromosikan dialog konstruktif dan terbuka dengan penganut agama lain.22 Platform digital dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi lintas batas ini.
Selain itu, Gereja dapat membangun komunitas digital yang mendukung kehidupan rohani umat dan menyediakan sarana konsultasi iman secara daring.17 Melalui platform ini, Gereja juga dapat meluncurkan kampanye sosial berbasis nilai-nilai Injil untuk membangun kesadaran akan isu-isu sosial yang relevan, seperti keadilan, perdamaian, dan lingkungan.17
Digitalisasi sebagai skala keterlibatan yang diperluas menunjukkan bahwa platform digital secara inheren menawarkan skala dan jangkauan yang jauh melampaui batas fisik tradisional. Sebuah Gereja lokal kini dapat terlibat dengan isu-isu global atau terhubung dengan individu di seluruh dunia. Digitalisasi bertindak sebagai penguat bagi GGM. Ini memungkinkan Gereja untuk memperluas keterlibatan sosialnya dari lokal ke global, untuk menumbuhkan “solidaritas lintas batas agama” 8, dan untuk mengatasi masalah dengan kecepatan dan visibilitas yang lebih besar. Ini berarti dampak sosial Gereja dapat diperbesar secara signifikan. Gereja harus secara strategis memanfaatkan alat digital tidak hanya untuk komunikasi internal tetapi untuk tindakan sosial eksternal. Ini termasuk berpartisipasi dalam advokasi online, membentuk koalisi virtual untuk keadilan, dan menggunakan wawasan berbasis data untuk mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan sosial di ranah digital.
Tantangannya adalah memastikan bahwa keterlibatan digital diterjemahkan menjadi dampak nyata di dunia nyata dan menghindari “aktivisme malas” (slacktivism) yang dangkal.
B. Pelayanan dan Kesaksian Digital: Membangun Komunitas dan Memberdayakan Umat
Pelayanan dan kesaksian Gereja di era digital harus beradaptasi untuk membangun komunitas yang kuat dan memberdayakan umat:
- Pelayanan Pastoral Daring: Media sosial menawarkan banyak peluang untuk pelayanan pastoral, seperti menjangkau umat yang tersebar, memberikan pembinaan iman daring melalui video, podcast, dan artikel, membangun komunitas digital yang mendukung kehidupan rohani, serta menyediakan sarana untuk konsultasi iman dan pendampingan rohani.17
- Pewartaan Injil: Gereja perlu meningkatkan intensitas pemanfaatan media sosial dan komunikasi virtual dalam menyampaikan dan menyebarluaskan berita Injil.22 Fokus utama harus pada menjangkau orang-orang yang belum mengenal iman Kristen sejati, bukan hanya mereka yang belum mengenal Gereja sebagai institusi.32 Ini menuntut strategi misi yang adaptif dan relevan dengan generasi Zillennial.32
- Pendidikan Agama Kristen (PAK) Digital: Pengembangan PAK sangat diperlukan agar relevan dengan kebutuhan jemaat dan mampu menjawab pengaruh perkembangan zaman, perubahan perilaku, serta ajaran menyimpang.4 Materi PAK harus sarat dengan muatan teologis dan dirumuskan secara teologis untuk memastikan kedalaman dan kebenaran iman.4
Transformasi ruang sakral dan komunitas di era digital menunjukkan bahwa platform digital digunakan untuk pelayanan pastoral, penginjilan, dan pendidikan Kristen.4 Aktivitas-aktivitas ini secara tradisional terjadi di ruang fisik, sakral (gedung gereja) dan dalam komunitas yang terikat secara geografis. Digitalisasi menantang definisi spasial dan komunal ini. Era digital mengubah sifat ruang sakral dan komunitas itu sendiri.
Ibadah online, persekutuan virtual, dan katekese digital menciptakan bentuk-bentuk “ekklesia” yang baru.24 Pertanyaannya bukan lagi apakah ini Gereja, tetapi bagaimana ini adalah Gereja. Ini menyiratkan pergeseran dari pemahaman Gereja yang murni teritorial menjadi yang lebih terhubung dan cair.
Gereja perlu mengembangkan “liturgi digital” dan “koinonia digital” yang kuat yang menumbuhkan perjumpaan spiritual sejati dan relasionalitas yang mendalam, daripada konsumsi yang dangkal. Ini memerlukan desain platform digital yang disengaja untuk mendorong partisipasi, interaksi, dan akuntabilitas, mengurangi risiko individualisme dan perilaku “anti-sosial”.2 Ini juga menyerukan evaluasi ulang peran pertemuan fisik dalam model Gereja hibrida.
C. Kerja Sama Lintas Sektor dan Advokasi Kebijakan Digital
Gereja dalam masyarakat digital juga memiliki peran krusial dalam kerja sama lintas sektor dan advokasi kebijakan, khususnya di ranah digital:
- Kolaborasi Lintas Sektor: Gereja dapat berkolaborasi secara efektif dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan komunitas lokal untuk mengatasi isu-isu sosial yang kompleks seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan polusi.8 Kemitraan ini dapat diperluas untuk mengatasi masalah digital, seperti kesenjangan akses internet atau penyalahgunaan data.
- Advokasi Kebijakan: Gereja harus mampu memberikan sumbangsih untuk meringankan beban pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial, misalnya melalui bakti sosial dan program gratis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.21 Lebih lanjut, Gereja memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memperjuangkan nasib rakyat yang lemah dan tidak berdaya secara politik.6 Di era digital, ini berarti Gereja harus memperluas advokasinya ke kebijakan digital, seperti hak digital, privasi data, dan melawan diskriminasi algoritmik.
Gereja sebagai aktor kunci dalam tata kelola digital menunjukkan bahwa GGM menekankan kolaborasi lintas sektor dan advokasi. Referensi menyebutkan kolaborasi Gereja dengan LSM/pemerintah, meringankan beban pemerintah, dan mengadvokasi kaum rentan.6 Ranah digital semakin diatur oleh kebijakan (misalnya, privasi data, moderasi konten, etika AI).
Jika Gereja ingin menjadi agen perubahan holistik, advokasinya harus meluas ke ruang kebijakan digital ini. Ini menyiratkan bahwa Gereja dipanggil untuk menjadi aktor kunci dalam tata kelola digital dan advokasi kebijakan. Sama seperti ia mengadvokasi kaum miskin di komunitas fisik, ia harus mengadvokasi hak-hak digital, inklusi digital, dan pengembangan digital yang etis. Ini adalah batas baru untuk keadilan sosial.
Gereja perlu mendidik para pemimpin dan anggotanya tentang isu-isu kebijakan digital, membentuk aliansi dengan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada hak-hak digital, dan memanfaatkan otoritas moralnya untuk memengaruhi pembuat kebijakan menuju masa depan digital yang lebih adil dan setara. Ini memerlukan sikap proaktif, bergerak melampaui reaksi terhadap masalah digital untuk secara aktif membentuk lanskap digital sesuai dengan nilai-nilai Injil.
D. Pendidikan dan Pemberdayaan Digital: Contoh-contoh Praktis
Gereja dapat mengimplementasikan GGM di era digital melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan yang memanfaatkan teknologi:
- Pelayanan Kesehatan Digital: Gereja dapat menyediakan layanan kesehatan terjangkau, terutama bagi yang kurang mampu, melalui platform digital atau informasi kesehatan online.8 Contohnya, telekonsultasi kesehatan, webinar kesehatan mental, atau kampanye kesadaran kesehatan melalui media sosial.
- Program Pendidikan Digital: Gereja memiliki sejarah panjang dalam membangun sekolah dan memberikan akses pendidikan bagi individu kurang mampu dan difabel.8 Di era digital, ini dapat diadaptasi melalui program pendidikan daring, kursus literasi digital, atau dukungan belajar
online untuk anak-anak dan remaja Gereja. - Advokasi Kebijakan Digital: Gereja dapat menjadi suara bagi komunitas yang terpinggirkan (minoritas, etnis, agama, miskin) dalam isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial.8 Di era digital, ini berarti advokasi untuk akses internet yang adil, perlindungan data pribadi, dan melawan diskriminasi algoritmik melalui petisi
online, kampanye media sosial, atau forum diskusi kebijakan publik digital. - Pemberdayaan Ekonomi Digital: Gereja dapat terlibat dalam gerakan solidaritas sosial yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi bagi komunitas miskin, termasuk program pengembangan keterampilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.8 Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan digital (misalnya, coding, e-commerce), pembentukan platform marketplace komunitas Gereja, atau crowdfunding untuk usaha mikro jemaat berbasis nilai.
- Pelayanan Sosial Digital: Gereja dapat membantu korban bencana alam melalui penggalangan dana online, menyediakan dukungan psikososial daring, atau membangun jaringan relawan digital untuk respons cepat.18 Layanan konseling pastoral daring juga menjadi bentuk pelayanan sosial yang relevan.
Digitalisasi sebagai enabler inklusi dan aksesibilitas menunjukkan bahwa contoh-contoh GGM mencakup kesehatan, pendidikan, advokasi, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial . Referensi memberikan contoh fisik.8 Teknologi digital memiliki kapasitas bawaan untuk menurunkan hambatan akses dan meningkatkan jangkauan. Program Pendidikan online dapat menjangkau siswa di daerah terpencil. Telemedisin dapat melayani mereka yang memiliki mobilitas terbatas. Advokasi digital dapat memobilisasi dukungan yang lebih luas.
Digitalisasi bertindak sebagai enabler yang kuat untuk GGM, terutama dalam mempromosikan inklusi dan aksesibilitas. Ini memungkinkan Gereja untuk memperluas layanannya ke populasi yang sebelumnya sulit dijangkau karena hambatan geografis, fisik, atau sosial-ekonomi.
Gereja harus berinvestasi secara strategis dalam infrastruktur digital dan pelatihan untuk memaksimalkan dampak inklusifnya. Ini berarti tidak hanya mereplikasi layanan yang ada secara online, tetapi berinovasi model diakonia digital baru yang memanfaatkan kemampuan unik teknologi untuk melayani kaum marjinal dan memberdayakan komunitas dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Ini juga menyiratkan mengatasi “kesenjangan digital” sebagai isu keadilan sosial.
Tabel 3: Tantangan dan Peluang Gereja di Era Digital
| Aspek | Tantangan | Peluang | ||
| Komunikasi & Interaksi | Ujaran kebencian, fitnah, hoaks.2 Anti-sosial & individualisme.2 | Jangkauan luas melalui media sosial.5 Komunitas digital.17 Konsultasi rohani daring.17 | ||
| Identitas & Teologi | Krisis identitas (divided self, imago meta).23 Teologi terdistorsi ( | Digital Docetism, Gnosticism).23 Transhumanisme & | cyborg.23 | Katekese kontekstual baru.3 Eklesiologi misioner diakronis.23 Re-evangelisasi & pemuridan digital.33 |
| Kebenaran & Otoritas | Simplifikasi kebenaran.27 Krisis otoritas (teolog amatir).27 | Pendidikan etika digital (anti-hoaks).17 Memperkuat landasan teologis (soteriologi, kristologi, eskatologi).23 | ||
| Pelayanan & Misi | Keengganan persekutuan luring.2 | Pembinaan iman daring.17 Pewartaan Injil virtual.22 Pelayanan diakonia digital (kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial).8 | ||
| Kerja Sama & Advokasi | – | Kerja sama lintas sektor digital.8 Advokasi kebijakan digital (hak digital, melawan | cybercrime).6 | |
Tabel 4: Contoh Implementasi Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM) di Era Digital
| Bidang GGM | Contoh Tradisional (dari Data) | Adaptasi Digital (Inferensi dari Data) |
| Keterlibatan Sosial & Kesejahteraan Bersama | Mediator rekonsiliasi, tempat belajar hidup damai.8 Perhatian pada isu kemanusiaan global.22 | Membangun komunitas digital yang mendukung kehidupan rohani.17 Kampanye sosial berbasis Injil via media sosial.17 Promosi dialog antar-agama daring.22 |
| Pelayanan & Kesaksian | Katekese, sakramen, pendalaman iman.18 Pemberitaan Injil.18 | Pembinaan iman daring (video, podcast, artikel).17 Pewartaan Injil melalui media sosial & komunikasi virtual.22 PAK digital.4 |
| Kerja Sama Lintas Sektor | Kolaborasi dengan NGO, pemerintah, komunitas lokal (mis. perubahan iklim, kemiskinan).8 Meringankan beban pemerintah.21 | Aliansi dengan organisasi hak digital. Kolaborasi dalam advokasi kebijakan digital (privasi data, AI etika). Proyek kesejahteraan sosial berbasis teknologi. |
| Pendidikan & Pemberdayaan | Mendirikan sekolah, akses pendidikan bagi kurang mampu/difabel.8 Program pengembangan keterampilan ekonomi.8 | Kursus literasi digital, e-learning. Pelatihan keterampilan digital (mis. coding, e-commerce). Platform marketplace komunitas Gereja, crowdfunding. |
| Peran Ganda Gereja | Menjaga ajaran/tradisi & beradaptasi dengan zaman.4 Milik Tuhan & persekutuan orang percaya.4 | Mempertahankan identitas inti sambil menyesuaikan metode pelayanan & komunikasi digital.2 Mengembangkan teologi kontekstual digital.3 |
| Contoh Spesifik GGM (Kueri) | Pelayanan Kesehatan, Program Pendidikan, Advokasi Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Sosial. | Pelayanan Kesehatan Digital: Telemedicine berbasis gereja, informasi kesehatan online. Program Pendidikan Digital: Webinar pendidikan moral/etika digital. Advokasi Kebijakan Digital: Petisi online untuk keadilan digital. Pemberdayaan Ekonomi Digital: Pelatihan e-commerce untuk UMKM. Pelayanan Sosial Digital: Penggalangan dana online, konseling daring. |
E. Peran Ganda Gereja: Menjaga Identitas dan Beradaptasi
Gereja di era digital menghadapi peran ganda yang krusial: menjaga identitas intinya sebagai penjaga ajaran dan tradisi, sekaligus beradaptasi secara fleksibel dengan perkembangan zaman.4 Ini adalah sebuah keseimbangan yang dinamis.
Di satu sisi, Gereja harus mempertahankan identitas fundamentalnya sebagai milik Tuhan (Kyriake) dan persekutuan orang percaya (Ekklesia) yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi umat-Nya.4 Hakikat spiritual ini tidak boleh dikompromikan. Di sisi lain, Gereja harus secara fleksibel menyesuaikan metode pelayanan dan komunikasinya di era digital agar tetap relevan dan efektif dalam menjangkau masyarakat kontemporer.2
Keseimbangan antara konservasi dan inovasi sebagai kunci relevansi adalah sebuah ketegangan klasik antara konservatisme (mempertahankan kebenaran inti) dan progresivisme (beradaptasi dengan konteks baru). Di era digital, ketegangan ini diperparah karena laju perubahan sangat cepat. Kuncinya bukanlah memilih salah satu, melainkan menemukan keseimbangan dinamis di mana kebenaran teologis inti dan identitas (misalnya, Imago Dei, Missio Dei, Inkarnasi) menyediakan fondasi yang stabil, sementara metode dan ekspresi pelayanan diadaptasi secara inovatif ke konteks digital. Inilah yang ingin dicapai oleh “teologi kontekstual” 3 dan “eklesiologi misioner”.23
Gereja perlu menumbuhkan budaya pembedaan teologis yang dapat membedakan antara kebenaran esensial yang harus dilestarikan dan ekspresi kontekstual yang harus diinovasi. Ini memerlukan pendidikan teologis berkelanjutan, dialog terbuka, dan kesediaan untuk bereksperimen dengan bentuk-bentuk pelayanan baru sambil tetap berlabuh pada prinsip-prinsip biblika. Kegagalan mencapai keseimbangan ini berisiko mengalami pembusukan (menjadi tidak relevan) atau pengenceran (kehilangan identitas).
VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi
A. Ringkasan Temuan Kunci
Analisis mendalam mengenai Gereja dalam masyarakat digital mengungkapkan beberapa temuan kunci:
- Gereja memiliki hakikat ganda sebagai entitas spiritual dan institusional, yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia melalui tiga tugas panggilan integral: koinonia, marturia, dan diakonia. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan holistik bagi masyarakat, bukan hanya spiritual.
- Landasan teologis yang kuat, berakar pada ajaran Alkitab, teladan inkarnasi Kristus, serta pemikiran para teolog dan filsuf Kristen terkemuka (seperti Timothy Keller, John Stott, Martin Luther King Jr., Richard Niebuhr, dan Max Weber), menegaskan imperatif Gereja untuk terlibat aktif dalam keadilan sosial dan pelayanan. Konsep Imago Dei dan Missio Dei menjadi fondasi misi transformatif Gereja.
- Masyarakat digital, dengan karakteristik “ruang imajiner” (cyberspace) dan dampaknya yang signifikan pada identitas, interaksi sosial, dan pembentukan komunitas, menghadirkan tantangan etika dan moralitas yang kompleks. Ini termasuk penyebaran disinformasi dan hoaks, krisis otoritas tradisional, simplifikasi kebenaran, kecenderungan anti-sosial, serta munculnya ideologi transhumanisme dan distorsi teologis seperti Digital Docetism dan Gnosticism.
- Namun, era digital juga membuka peluang besar bagi Gereja untuk memperluas jangkauan pelayanan, memperbarui katekese, dan menerapkan eklesiologi misioner diakronis. Landasan teologis yang relevan (soteriologi, kristologi, eskatologi) memberikan jangkar bagi Gereja untuk menavigasi kompleksitas ini.
- Implementasi Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM) di era digital menuntut Gereja untuk terlibat dalam keterlibatan sosial, pelayanan, kesaksian, kerja sama lintas sektor, pendidikan, dan pemberdayaan melalui platform digital. Hal ini memerlukan keseimbangan yang cermat antara menjaga identitas inti dan beradaptasi secara inovatif.
B. Rekomendasi Strategis untuk Gereja di Era Digital
Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah rekomendasi strategis bagi Gereja untuk menjadi Gereja yang relevan dan berdampak di era digital:
- Penguatan Teologi Kontekstual Digital: Gereja perlu secara proaktif mengembangkan pemahaman teologis yang mendalam tentang teknologi dan dampaknya. Ini krusial untuk merumuskan respons iman yang relevan dan biblika terhadap tantangan kontemporer seperti transhumanisme, cyborg, dan krisis identitas digital. Teologi ini harus mampu mengartikulasikan bagaimana kebenaran Kristen berinteraksi dengan dan mengkritik filosofi yang mendasari dunia digital.
- Investasi dalam Katekese dan Pemuridan Digital: Merancang dan mengimplementasikan program pendidikan agama Kristen yang adaptif, interaktif, dan berlandaskan teologi yang kuat adalah esensial. Program ini harus membekali jemaat dengan etika digital yang kokoh, kemampuan kritis dalam menyaring informasi (termasuk melawan hoaks dan disinformasi), serta membangun identitas Kristen yang otentik dan tidak terpecah di ruang daring.
- Optimalisasi Media Digital untuk GGM: Gereja harus secara strategis memanfaatkan media sosial dan platform virtual untuk memperluas implementasi GGM. Ini mencakup pelayanan diakonia (misalnya, pelayanan kesehatan daring, program pendidikan digital, pemberdayaan ekonomi melalui platform e-commerce komunitas, dan pelayanan sosial daring), marturia (pewartaan Injil yang kontekstual dan advokasi keadilan digital), serta koinonia (pembentukan komunitas digital yang otentik dan interaktif yang melampaui batas fisik).
- Membangun Kemitraan Lintas Sektor Digital: Gereja didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lain dalam advokasi kebijakan digital. Ini termasuk memperjuangkan hak-hak digital, melawan cybercrime, mengatasi kesenjangan digital, dan berpartisipasi dalam proyek-proyek kesejahteraan sosial yang memanfaatkan teknologi. Gereja harus menjadi aktor kunci dalam tata kelola digital.
- Pembinaan Kepemimpinan Digital: Melatih pemimpin Gereja dan jemaat untuk menjadi “digital native” yang cakap secara teologis dan teknologis adalah prioritas. Mereka harus mampu memimpin pelayanan dan membangun komunitas secara terintegrasi di lingkungan fisik dan virtual, memahami dinamika dan tantangan unik dari setiap ranah.
C. Arah Penelitian Lanjutan
Untuk memperdalam pemahaman dan efektivitas Gereja di era digital, beberapa arah penelitian lanjutan yang disarankan meliputi:
- Studi empiris tentang efektivitas model pelayanan Gereja digital di berbagai konteks denominasi dan budaya di Indonesia, termasuk analisis dampak kuantitatif dan kualitatif.
- Penelitian mendalam tentang dampak psikologis dan sosiologis dari “diri terbelah” (divided self) di era digital terhadap spiritualitas dan identitas jemaat, serta strategi pastoral untuk mengatasinya.
- Pengembangan kerangka etika Kristen yang komprehensif untuk kecerdasan buatan (AI), realitas virtual (VR), dan teknologi baru lainnya, termasuk implikasi teologis dan moralnya.
- Analisis perbandingan strategi Gerakan Gereja dan Masyarakat (GGM) di era digital antara Gereja-gereja di negara berkembang dan negara maju, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan unik.
Karya yang dikutip
- Pemahaman Masyarakat dan Masyarakat Digital – Kabupaten Tegal, diakses Juli 3, 2025, https://tegalkab.go.id/news/view/artikel/pemahaman_masyarakat_dan_masyarakat_digital_20220704110450
- pelayanan gereja di era digital berdasarkan analisis deskriptif kisah …, diakses Juli 3, 2025, https://ojs.stakrri.ac.id/index.php/theologiainsani/article/download/72/50/695
- Transformasi Media Digital dalam Katekese Kontekstual: Studi …, diakses Juli 3, 2025, https://ejurnal.stpdianmandala.ac.id/index.php/magistra/article/view/50
- 21 TEOLOGI SEBAGAI LANDASAN BAGI GEREJA DALAM … – UKI, diakses Juli 3, 2025, https://ejournal.uki.ac.id/index.php/shan/article/download/1766/1352
- MISI GEREJA DI ERA DIGITAL: PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK MENJANGKAU GENERASI BARU | Jurnal Komunikasi, diakses Juli 3, 2025, https://jkm.my.id/index.php/komunikasi/article/view/14
- Teologia Pembebasan: Kajian Peranan Gereja Dalam …, diakses Juli 3, 2025, https://melo.iakn-toraja.ac.id/index.php/ojsmelo/article/download/27/9
- Peran Gereja dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat …, diakses Juli 3, 2025, https://journal.sttpadonaybatu.ac.id/index.php/YJTBR/article/download/18/7
- Kontribusi dan Peran Gereja dalam Membangun Solidaritas …, diakses Juli 3, 2025, https://ejurnal.stpkat.ac.id/index.php/lumen/article/download/464/519/1848
- Sistem Hierarki Gereja Bala Keselamatan (Studi Eklesiologi tentang …, diakses Juli 3, 2025, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6836/2/T1_712007084_BAB%20II.pdf
- Konsep Paulus Tentang Gereja | In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi, diakses Juli 3, 2025, https://journal.actual-insight.com/index.php/intheos/article/view/1471
- MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA | JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL – Dinasti Review, diakses Juli 3, 2025, https://dinastirev.org/jmpis/article/view/253
- MEMAHAMI MASYARAKAT DAN PERSPEKTIFNYA Donny Prasetyo , Irwansyah Universitas Pelita Harapan Indonesia Universitas Indonesia, Jak, diakses Juli 3, 2025, https://dinastirev.org/JMPIS/article/download/253/145/512
- Sociology Field of study, diakses Juli 3, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
- Materi Sosiologi Kelas X SMA: Fungsi dan Unsur-Unsur Masyarakat …, diakses Juli 3, 2025, https://kids.grid.id/read/473782134/materi-sosiologi-kelas-x-sma-fungsi-dan-unsur-unsur-masyarakat?page=all
- Matius 5:13-14 – Alkitab SABDA, diakses Juli 3, 2025, https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=matius%205:%2013-14
- Australia > Mat 5:13-16 “Born Again Identity: Garam … – ICC Melbourne, diakses Juli 3, 2025, https://www.icc-melbourne.org/icc-blog/post/mat-513-16–born-again-identity-garam-dan-terang-dunia-
- Media Sosial dan Pelayanan Pastoral Gereja Katolik – Keuskupan …, diakses Juli 3, 2025, https://keuskupanagungkupang.org/2025/03/27/media-sosial-dan-pelayanan-pastoral-gereja-katolik/
- 7 Peran Gereja Dalam Masyarakat Majemuk | PDF – Scribd, diakses Juli 3, 2025, https://id.scribd.com/document/504237335/7-Peran-Gereja-Dalam-Masyarakat-Majemuk
- Relasi Gereja, Negara, dan Masyarakat: Etika Kristen pada …, diakses Juli 3, 2025, https://jurnal.widyaagape.ac.id/index.php/jrsc/article/download/108/92/
- Peran Gereja Protestan Dalam Gerakan Keadilan Sosial: Antara Ajaran Injil dan Realitas Maskyarakat Sumatera Utara – ResearchGate, diakses Juli 3, 2025, https://www.researchgate.net/publication/386360579_Peran_Gereja_Protestan_Dalam_Gerakan_Keadilan_Sosial_Antara_Ajaran_Injil_dan_Realitas_Maskyarakat_Sumatera_Utara
- Analisis Peran Gereja Dalam Penyelenggaraan Keadilan Sosial di …, diakses Juli 3, 2025, https://www.kompasiana.com/harold6969/61dd55be4b660d1a44726404/analisis-peran-gereja-dalam-penyelenggaraan-keadilan-sosial-di-masyarakat-indonesia
- Teologi Misi Bagi Gerakan Misi dan Komunikasi Kristen Pasca …, diakses Juli 3, 2025, https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/article/view/377
- MISIONAL EKLESIOLOGI BUDAYA DIGITAL … – JURNAL SETIA, diakses Juli 3, 2025, https://jurnal.sttsetia.ac.id/index.php/phr/article/download/422/208/3273
- Digital Ecclesia Sebagai Gereja Sinodal yang Mendengarkan …, diakses Juli 3, 2025, https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/962
- MASYARAKAT INFORMASI DAN DIGITAL: – Neliti, diakses Juli 3, 2025, https://media.neliti.com/media/publications/41503-none-dcf5b5fa.pdf
- Theologies of the Digital, diakses Juli 3, 2025, https://www.theologies-of-the-digital.org/
- Filsafat Ilmu Teologi dalam Era Digital – Asosiasi Riset Ilmu …, diakses Juli 3, 2025, https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpakk/article/download/983/1385/5411
- Pandangan Etika Kristen Terhadap Teknologi | PDF | Politik – Scribd, diakses Juli 3, 2025, https://id.scribd.com/presentation/488165799/PANDANGAN-ETIKA-KRISTEN-TERHADAP-TEKNOLOGI
- Etika Kristen dan Teknologi Informasi Sebuah Tinjauan Menurut Perspektif Alkitab, diakses Juli 3, 2025, https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/349
- Inilah Tiga Langkah Pemerintah Cegah Penyebaran Hoaks Melalui Medsos – Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, diakses Juli 3, 2025, https://setkab.go.id/inilah-tiga-langkah-pemerintah-cegah-penyebaran-hoaks-melalui-medsos/
- Pandangan Gereja Tentang Media Sosial | PDF – Scribd, diakses Juli 3, 2025, https://id.scribd.com/document/662585008/Pandangan-Gereja-Tentang-Media-Sosial
- Strategi Pelayanan Misi Gereja di Era Digital dan Integrasi …, diakses Juli 3, 2025, https://ejournal.iaknpky.ac.id/index.php/pambelum/article/view/187
- (PDF) Strategi gereja-gereja daerah menyikapi tantangan pelayanan – ResearchGate, diakses Juli 3, 2025, https://www.researchgate.net/publication/359238169_Strategi_gereja-gereja_daerah_menyikapi_tantangan_pelayanan