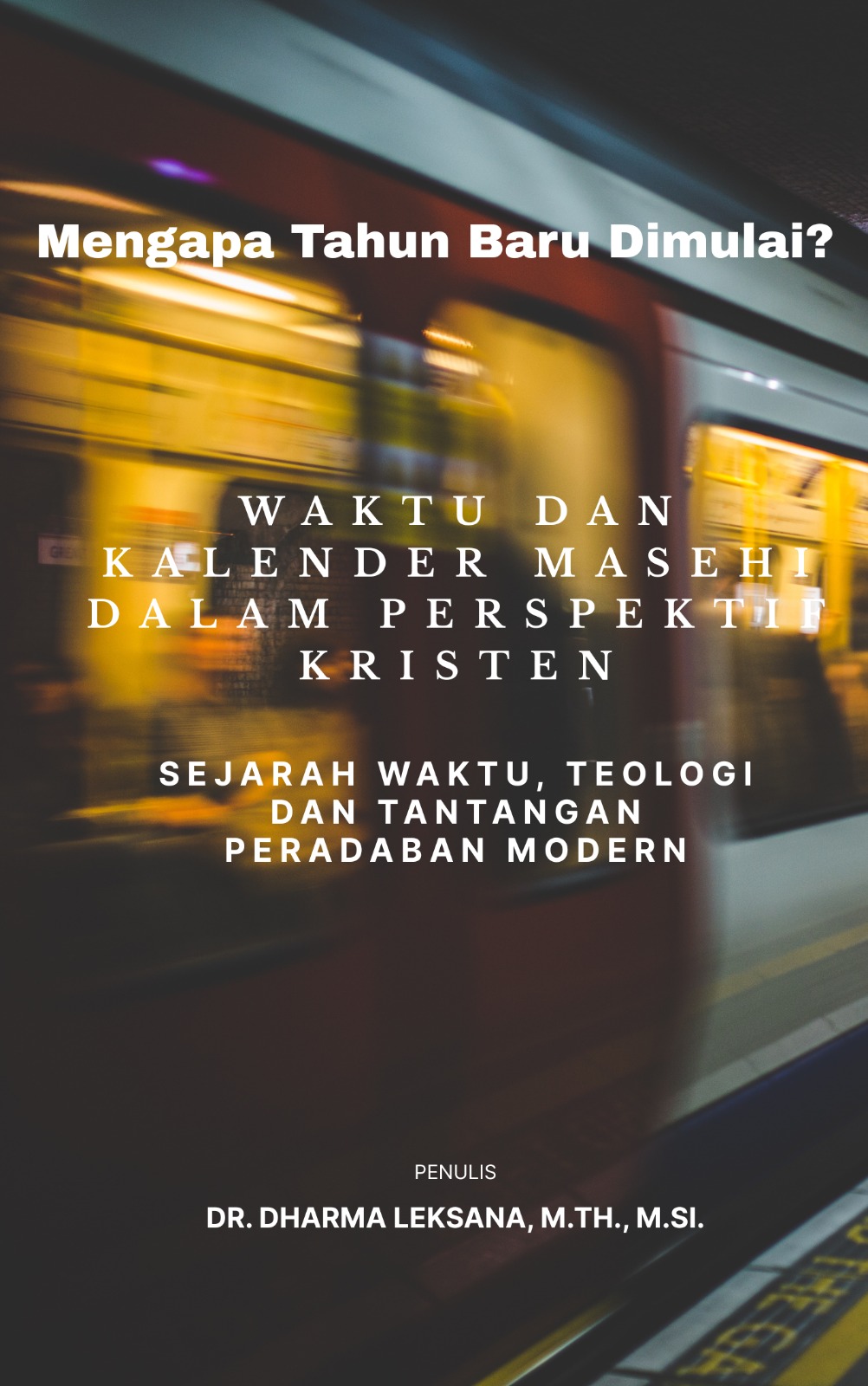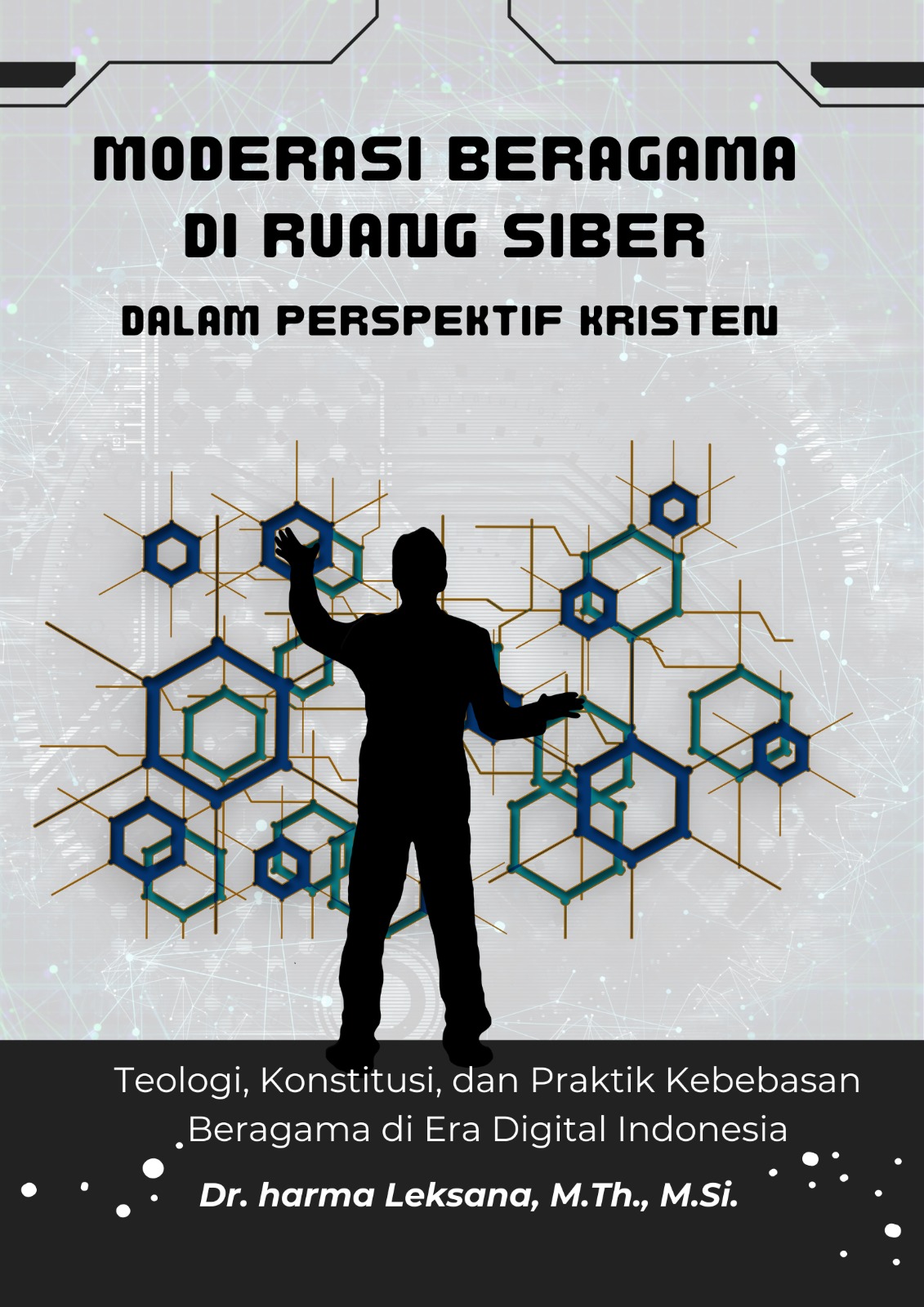Jika Yesus Punya Akun Medsos, Apa yang Dia Lakukan?

(Refleksi Teologi Komunikasi di Era Digital)
Oleh : Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.
Pendahuluan: Dari Galilea ke Timeline
Bayangkan sejenak: Yesus punya akun Instagram, Twitter, atau TikTok. Apa yang akan Ia unggah? Apakah perumpamaan tentang anak yang hilang akan tampil dalam bentuk video pendek dengan musik latar sendu? Apakah khotbah di bukit akan disiarkan live streaming ke ribuan follower? Pertanyaan ini bukan sekadar imajinasi ringan, melainkan undangan untuk berpikir lebih dalam: bagaimana Yesus berkomunikasi, bagaimana gereja menafsirkan pola itu sepanjang sejarah, dan apa artinya bagi kita yang hidup dalam dunia digital dengan arsitektur komunikasi baru—media sosial, algoritma, dan banjir informasi.
Teologi komunikasi memberi kita pintu masuk untuk merenungkan isu ini. Ia berangkat dari keyakinan bahwa Allah adalah komunikator agung, yang menyatakan diri-Nya kepada manusia dan membangun relasi dengan kasih. Komunikasi, dalam perspektif ini, bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan perjumpaan eksistensial antara Allah dan manusia, serta antar manusia itu sendiri.
1. Fondasi Teologis Komunikasi Yesus dalam Injil Sinoptik
Injil Matius, Markus, dan Lukas memotret Yesus sebagai komunikator yang unik. Ia tidak menulis buku teologi, tidak mendirikan institusi komunikasi, bahkan tidak mengajarkan retorika formal. Namun, cara Ia menyampaikan pesan membentuk fondasi teologi komunikasi Kristen.
Perumpamaan sebagai “meme rohani”
Yesus mengajarkan dengan perumpamaan: benih yang jatuh di tanah, domba yang hilang, seorang Samaria yang murah hati. Bagi kita yang hidup di era media digital, perumpamaan ini mirip dengan meme: singkat, sederhana, mudah diingat, dapat diteruskan secara viral dari mulut ke mulut. Filosof Paul Ricoeur menyebut perumpamaan sebagai disclosure—ungkapan simbolis yang membuka horizon baru dalam memahami realitas ilahi.^1
Komunikasi di ruang publik
Yesus tidak mengurung diri dalam ruang privat. Ia hadir di pasar, tepi danau, jalan raya, rumah makan, bahkan di rumah orang berdosa. Ia memilih ruang sosial sebagai panggung komunikasi. Jika ditranslasikan ke era kita, itu berarti Yesus tidak akan mengurung pesan-Nya dalam ruang sakral semata, tetapi hadir di timeline, komentar, podcast, forum daring—di mana manusia berkumpul dan bercakap.
Medium sekaligus pesan
Marshall McLuhan, teoritikus komunikasi abad ke-20, pernah mengatakan: “The medium is the message.”^2 Yesus bukan hanya menyampaikan Injil, Ia sendiri adalah Injil yang hidup. Dalam diri-Nya, medium dan pesan menyatu: hidup-Nya adalah berita. Dengan kata lain, komunikasi Yesus bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tindakan, sikap, dan relasi yang dibangun.
Dimensi relasional
Agustinus dan Thomas Aquinas menekankan bahwa komunikasi Kristen berakar pada kasih.^3 Kasih menata komunikasi dalam relasi Aku–Engkau (meminjam istilah Martin Buber), di mana yang terpenting bukan informasi, melainkan transformasi.^4 Yesus selalu berbicara dari cinta, bahkan ketika menegur keras.
2. Pola Komunikasi: Dari Gereja Perdana ke Modern
Sejarah gereja dapat dibaca sebagai sejarah komunikasi Injil. Metode, medium, dan gaya selalu berubah, tetapi roh komunikasinya—kasih Allah yang ingin dikenal—tetap sama.
Gereja Perdana
Komunikasi Injil bermula dalam komunitas kecil. Surat-surat Paulus adalah “email pastoral” abad pertama: personal, kontekstual, ditujukan ke komunitas tertentu, tetapi kemudian disalin dan diedarkan lebih luas. Kisah Para Rasul menunjukkan model komunikasi yang dialogis, dari sinagoga ke pasar, dari perdebatan publik ke percakapan pribadi.
Abad Pertengahan
Mayoritas orang awam buta huruf. Gereja lalu memakai ikon, mozaik, arsitektur katedral, liturgi dramatis sebagai “media massa” zamannya.^5 Dinding katedral menjadi “Instagram” abad pertengahan: gambar visual yang menceritakan kisah Injil.
Reformasi dan Cetak
Revolusi Gutenberg mengubah wajah komunikasi. Luther menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman, mencetak pamflet, menulis nyanyian jemaat. Reformasi adalah bukti bagaimana teknologi komunikasi baru—mesin cetak—menjadi katalis perubahan teologis besar.^6
Era Modern: Radio dan Televisi
Abad ke-20 menghadirkan gelombang baru: Billy Graham memakai televisi untuk menginjili jutaan orang. Radio gereja, televisi rohani, majalah Kristen—semua adalah perpanjangan komunikasi Injil.
Internet dan Media Sosial
Kini komunikasi bergerak ke dunia daring. Dari situs web, YouTube, Instagram, TikTok, hingga podcast, gereja berupaya menjangkau audiens yang semakin cair dan global.
3. Jika Yesus Punya Akun Medsos
Bayangkan akun Yesus di Twitter/X. Bio-Nya mungkin berbunyi: “Jalan, Kebenaran, dan Hidup. DM terbuka untuk siapa saja.”
Yesus tidak sibuk mengejar jumlah likes atau followers. Ia justru mungkin menantang logika algoritma: menyeberang ke akun dengan nol follower, mengangkat suara mereka yang tak terdengar. Konten-Nya mungkin sederhana—sebuah perumpamaan singkat di thread, sebuah kisah penyembuhan dalam video 1 menit, sebuah doa singkat di Instagram Story—namun menyentuh hati.
Kisah anak hilang bisa menjadi short video paling banyak dishare, karena setiap orang merasa terwakili dalam kerinduan pulang. Khotbah di bukit bisa muncul sebagai carousel post dengan kalimat sederhana: “Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah.”
Berbeda dari algoritma komersial yang mengejar engagement, Yesus mengedepankan algoritma kasih. Ia mendahulukan yang terpinggirkan—akun anonim, orang yang terban dari komunitas digital, suara yang dicemooh.
Yesus tidak akan meladeni toxic debate dengan kebencian. Ia bisa menjawab dengan tanya balik yang menusuk hati, seperti kepada orang Farisi. Hoaks dibantah dengan “Aku adalah kebenaran.” Cancel culture dihadapi dengan pengampunan: “Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan melempar komentar pertama.”
Yesus tidak sekadar membangun follower, tetapi membentuk komunitas. Media sosial bagi-Nya bukan panggung narsistik, melainkan sarana untuk membangun “ekklesia digital.”
4. Relevansi Teologi Komunikasi Yesus di Era Digital
Kita hidup dalam zaman information overload: banjir data, opini, dan distraksi. Hoaks, ujaran kebencian, deepfake, dan bias algoritma merusak kualitas komunikasi.
Kesederhanaan di tengah noise
Yesus tidak pernah membanjiri orang dengan kata-kata berlebihan. Perumpamaan-Nya singkat, namun penuh makna. Dalam banjir konten, teologi komunikasi Yesus menegaskan pentingnya clarity over quantity—kualitas pesan lebih penting daripada banyaknya postingan.
Relasi personal dan publik
Yesus menyeimbangkan komunikasi personal (Nikodemus di malam hari, perempuan Samaria di sumur) dengan komunikasi publik (khotbah di bukit, masuk Yerusalem). Gereja digital juga harus seimbang: membangun percakapan personal (chat, DM, konseling online) dan kesaksian publik (podcast, live streaming, artikel).
Kontekstualisasi digital
Yesus memakai bahasa sehari-hari: benih, gandum, domba, rumah. Kontekstualisasi hari ini berarti memakai bahasa meme, video pendek, bahkan emoji—tanpa mengurangi kedalaman.^7
Menembus hambatan algoritma
Algoritma media sosial menentukan siapa yang melihat apa. Tetapi Injil dipanggil untuk menembus batas itu. Yesus hadir di antara mereka yang tak terlihat—dan kita pun dipanggil untuk menyasar ruang-ruang digital yang sepi dari perhatian.
5. Penutup: Yesus vs. Algoritma
Pertanyaan “Jika Yesus punya akun medsos, apa yang Ia lakukan?” sejatinya adalah cermin bagi kita. Apakah kita, sebagai pengikut-Nya, membiarkan algoritma digital menentukan siapa yang kita dengar, siapa yang kita abaikan? Ataukah kita meniru Sang Guru yang selalu menyeberang batas, mencari yang hilang, dan menghadirkan kasih di ruang yang paling bising sekalipun?
Jika Yesus hadir di media sosial, Ia mungkin tidak sibuk mencari verified badge. Ia justru hadir untuk memverifikasi kemanusiaan setiap orang, memastikan tidak ada yang tersisih dari percakapan kasih.
Teologi komunikasi mengingatkan kita: Allah adalah komunikator agung. Yesus adalah pesan sekaligus medium. Roh Kudus adalah dinamika yang membuat pesan itu hidup di setiap zaman, termasuk zaman digital. Dan kita? Dipanggil menjadi komunikator Injil—bukan dengan suara yang paling keras, tetapi dengan cinta yang paling nyata.
#AlgoritmaYesus
#MedosYesus
#TeologiKomunikasi
#JikaYesusBermediaSosial
#AkuMedsosYesus
#YesusDanMedsos
Catatan Kaki
- Paul Ricoeur, Figuring the Sacred: Religion, Narrative, and Imagination, trans. David Pellauer (Minneapolis: Fortress Press, 1995), 161–176.
- Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: McGraw-Hill, 1964), 7.
- Augustine, De Doctrina Christiana, trans. R. P. H. Green (Oxford: Clarendon Press, 1995), I.36.
- Martin Buber, I and Thou, trans. Walter Kaufmann (New York: Scribner, 1970), 62–63.
- Hans Belting, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art, trans. Edmund Jephcott (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 112–145.
- Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 71–98.
- Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London: Methuen, 1982), 36–41.
Daftar Pustaka
Barth, Karl. Church Dogmatics I/1: The Doctrine of the Word of God. Edinburgh: T&T Clark, 1936.
Buber, Martin. I and Thou. Translated by Walter Kaufmann. New York: Charles Scribner’s Sons, 1970.
Ellul, Jacques. The Humiliation of the Word. Grand Rapids: Eerdmans, 1985.
Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Boston: Beacon Press, 1984.
McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill, 1964.
Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London: Methuen, 1982.
Ricoeur, Paul. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.
Ricoeur, Paul. Time and Narrative. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Shannon, Claude E., and Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press, 1949.
Ward, Graham. Theology and Contemporary Critical Theory. London: Macmillan, 1996. Zizioulas, John D. Being as Communion: Studies in Personhood and the Church. Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press, 1985.